Pengemis dan Problematika di Ibukota
Salah satu episode acara John Pantau di salah satu stasiun TV berkisah mengenai para pengemis. Para pengemis yang kerap 'berkeliaran' di ibukota dan menunjukkan penampilan memelas ternyata tidak sungguhan. Seorang Bapak yang memperlihatkan penampilan kakinya yang buntung, ternyata tidak sungguh-sungguh buntung. Begitu pula dengan seorang paruh baya yang memperban kakinya seolah mengalami kecelakaan. Seolah menjadi kata yang tepat karena kaki tersebut sama sekali tidak terluka. Berdasarkan pengakuan mereka sendiri dalam acara tersebut, rekayasa penampilan tersebut memang sengaja ditunjukkan sebagai katalis profesi mereka. Ya, mereka memanfaatkan rasa iba orang lain untuk memperoleh untuk yang lebih besar. Penderitaan cenderung mendatangkan rasa iba bukan?
Maraknya pengemis khususnya di Ibukota ternyata memang didasarkan pada suatu fakta bahwa 'profesi' seperti itu cukup menjanjikan dari segi finansial. Untuk ukuran ibukota, penghasilan yang dapat mereka peroleh dari mengemis bisa jadi setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan karyawan kantoran biasa. Dengan tingkat pendidikan yang bisa dibilang tidak terlalu tinggi, berusaha bertahan hidup di rimba ibu kota memang kerap menjadi problematika tersendiri. Jika ada kesempatan untuk berhasil, terlepas dari cara apa yang ditempuh, kenapa tidak diambil?
Setidaknya ada dua perspektif yang dirasakan dari kehadiran pengemis di Ibukota. Pertama, dari perspektif masyarakat yang berada di strata lebih tinggi, kehadiran mereka memang dianggap mendatangkan rasa tidak nyaman selain mengurangi tingkat estetika kota. Kedua, persoalan pertama tersebut disandingkan dengan 'keterpaksaan' masyarakat kelas bawah di mana persaingan memperebutkan hidup itu sendiri terlihat dengan jelas. Hal ini berdampak pada menurunnya sikap mental positif di kalangan mereka. Masalah dipandang dari perspektif pengemis, kendati mereka tidak sadar. Contohnya, penurunan semangat berusaha secara mandiri (malas), pembiasaan terhadap kultur meminta-minta yang notabene tidak dikehendaki agama, pembiasaan perilaku berbohong, menurunnya tingkat pendidikan serta kesehatan anak-anak mereka, dan lain sebagainya.
Intinya, kehadiran pengemis di Ibukota memang mendatangkan mudharat bagi kedua pihak. Satu-satunya alasan yang meringankan aktivitas mereka adalah himpitan ekonomi yang didukung oleh sikap mental yang sudah jatuh. Sampai di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa salah satu solusi yang dapat dilakukan untu menekan hal tersebut adalah peningkatan kesejahteraan pengemis melalui pengembangan sektor ekonomi. Namun ternyata dalam kenyataannya tidak semulus yang diharapkan. Pertama, karena pengembangan sektor ekonomi masih memerlukan SDM dengan kompetensi khusus. Para pengemis yang belum memiliki kompetensi itu otomatis akan tersisih, atau paling tidak dibutuhkan effort tambahan untuk memberikan kompetensi itu. Kedua, karena mental para pengemis yang sudah jatuh, di mana mereka sudah merasa pekerjaan itu sebagai zona nyaman mereka. Penulis pernah menjumpai fakta di lapangan bahwa ketika mereka ditanya mengenai kemungkinan perubahan mata pencaharian, masa depan, atau hal-hal sejenis lainnya, tidak sedikit mereka yang lebih memiliki bertahan dengan kondisi asal yang seperti itu. Tidak heran, program-program satu lini dari pemerintah kerap gagal menyelesaikan polemik ini.
Para pengemis yang ada sekarang ini bisa terdiri dari generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama maksudnya adalah para perantauan yang mengadu nasib ke ibukota demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik namun gagal di tengah jalan. Sedangkan generasi kedua maksudnya adalah keturunan dari generasi pertama. Perbedaan generasi berdampak pada perbedaan karakter personal masing-masing individu. Dua hal ini juga menyebabkan dibutuhkannya perbedaan penanganan. Maka betambah kompleks pula permasalahan pengemis di Ibukota.
Tidak ada formula generik sebagai solusi atas permasalahan ini karena setiap kasus seyogianya ditangani secara spesifik. Namun setidaknya, ada tiga aspek yang satu sama lain saling terkait dengan pencegahan perluasana serta kontinuitas masalah. Pertama, program peningkatan kesejahteraan di daerah-daerah perlu digalakkan mengingat sangat banyak para pengemis merupakan penduduk daerah yang melakukan urbanisasi. Jika di daerah asalnya mereka dapat memperoleh kesejahteraan, tingkat urbanisasi dapat ditekan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakkan agroindustri berbasis pedesaan, disertai pemberian akses terhadap informasi teknologi, pasar, dan kemitraan. Kedua, sikap mental dibentuk melalui pendidikan. Dengan demikian, sudah saatnya pendidikan digalakkan di daerah-daerah. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidian legal formal seperti selama ini dilakukan, tapi lebih kepada pendidikan berbasis kompetensi di mana siswa disosialisasikan dengan potensi diri dan daerahnya untuk membangun usaha. Ketiga, pembinaan spiritual yang digalakkan melalui kegiatan-kegiatan dakwah. Hal ketiga ini belum banyak pihak yang melirik, padahal kontribusinya bagi pembangunan mental luar biasa besar. Spiritualitas yang tinggi memungkinkan potensi manusia dalam diri seseorang melejit dan lebih stabil dalam menyikapi hidup.
Berbicara sampai kapan pun akan selalu lebih mudah daripada melakukan. Memberikan komentar selalu lebih gampang ketimbang merasakan di dunia nyata. Persoalannya sekarang adalah, bukan berarti berbicara dan berkomentar itu dilarang tetapi lebih dari itu, segala yang diungkapkan memerlukan aktualisasi lebih lanjut. Seribu jejak selalu dimulai dari satu jejak.
Wallohua'lam bishowab
Maraknya pengemis khususnya di Ibukota ternyata memang didasarkan pada suatu fakta bahwa 'profesi' seperti itu cukup menjanjikan dari segi finansial. Untuk ukuran ibukota, penghasilan yang dapat mereka peroleh dari mengemis bisa jadi setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan karyawan kantoran biasa. Dengan tingkat pendidikan yang bisa dibilang tidak terlalu tinggi, berusaha bertahan hidup di rimba ibu kota memang kerap menjadi problematika tersendiri. Jika ada kesempatan untuk berhasil, terlepas dari cara apa yang ditempuh, kenapa tidak diambil?
Setidaknya ada dua perspektif yang dirasakan dari kehadiran pengemis di Ibukota. Pertama, dari perspektif masyarakat yang berada di strata lebih tinggi, kehadiran mereka memang dianggap mendatangkan rasa tidak nyaman selain mengurangi tingkat estetika kota. Kedua, persoalan pertama tersebut disandingkan dengan 'keterpaksaan' masyarakat kelas bawah di mana persaingan memperebutkan hidup itu sendiri terlihat dengan jelas. Hal ini berdampak pada menurunnya sikap mental positif di kalangan mereka. Masalah dipandang dari perspektif pengemis, kendati mereka tidak sadar. Contohnya, penurunan semangat berusaha secara mandiri (malas), pembiasaan terhadap kultur meminta-minta yang notabene tidak dikehendaki agama, pembiasaan perilaku berbohong, menurunnya tingkat pendidikan serta kesehatan anak-anak mereka, dan lain sebagainya.
Intinya, kehadiran pengemis di Ibukota memang mendatangkan mudharat bagi kedua pihak. Satu-satunya alasan yang meringankan aktivitas mereka adalah himpitan ekonomi yang didukung oleh sikap mental yang sudah jatuh. Sampai di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa salah satu solusi yang dapat dilakukan untu menekan hal tersebut adalah peningkatan kesejahteraan pengemis melalui pengembangan sektor ekonomi. Namun ternyata dalam kenyataannya tidak semulus yang diharapkan. Pertama, karena pengembangan sektor ekonomi masih memerlukan SDM dengan kompetensi khusus. Para pengemis yang belum memiliki kompetensi itu otomatis akan tersisih, atau paling tidak dibutuhkan effort tambahan untuk memberikan kompetensi itu. Kedua, karena mental para pengemis yang sudah jatuh, di mana mereka sudah merasa pekerjaan itu sebagai zona nyaman mereka. Penulis pernah menjumpai fakta di lapangan bahwa ketika mereka ditanya mengenai kemungkinan perubahan mata pencaharian, masa depan, atau hal-hal sejenis lainnya, tidak sedikit mereka yang lebih memiliki bertahan dengan kondisi asal yang seperti itu. Tidak heran, program-program satu lini dari pemerintah kerap gagal menyelesaikan polemik ini.
Para pengemis yang ada sekarang ini bisa terdiri dari generasi pertama dan generasi kedua. Generasi pertama maksudnya adalah para perantauan yang mengadu nasib ke ibukota demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik namun gagal di tengah jalan. Sedangkan generasi kedua maksudnya adalah keturunan dari generasi pertama. Perbedaan generasi berdampak pada perbedaan karakter personal masing-masing individu. Dua hal ini juga menyebabkan dibutuhkannya perbedaan penanganan. Maka betambah kompleks pula permasalahan pengemis di Ibukota.
Tidak ada formula generik sebagai solusi atas permasalahan ini karena setiap kasus seyogianya ditangani secara spesifik. Namun setidaknya, ada tiga aspek yang satu sama lain saling terkait dengan pencegahan perluasana serta kontinuitas masalah. Pertama, program peningkatan kesejahteraan di daerah-daerah perlu digalakkan mengingat sangat banyak para pengemis merupakan penduduk daerah yang melakukan urbanisasi. Jika di daerah asalnya mereka dapat memperoleh kesejahteraan, tingkat urbanisasi dapat ditekan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggalakkan agroindustri berbasis pedesaan, disertai pemberian akses terhadap informasi teknologi, pasar, dan kemitraan. Kedua, sikap mental dibentuk melalui pendidikan. Dengan demikian, sudah saatnya pendidikan digalakkan di daerah-daerah. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidian legal formal seperti selama ini dilakukan, tapi lebih kepada pendidikan berbasis kompetensi di mana siswa disosialisasikan dengan potensi diri dan daerahnya untuk membangun usaha. Ketiga, pembinaan spiritual yang digalakkan melalui kegiatan-kegiatan dakwah. Hal ketiga ini belum banyak pihak yang melirik, padahal kontribusinya bagi pembangunan mental luar biasa besar. Spiritualitas yang tinggi memungkinkan potensi manusia dalam diri seseorang melejit dan lebih stabil dalam menyikapi hidup.
Berbicara sampai kapan pun akan selalu lebih mudah daripada melakukan. Memberikan komentar selalu lebih gampang ketimbang merasakan di dunia nyata. Persoalannya sekarang adalah, bukan berarti berbicara dan berkomentar itu dilarang tetapi lebih dari itu, segala yang diungkapkan memerlukan aktualisasi lebih lanjut. Seribu jejak selalu dimulai dari satu jejak.
Wallohua'lam bishowab
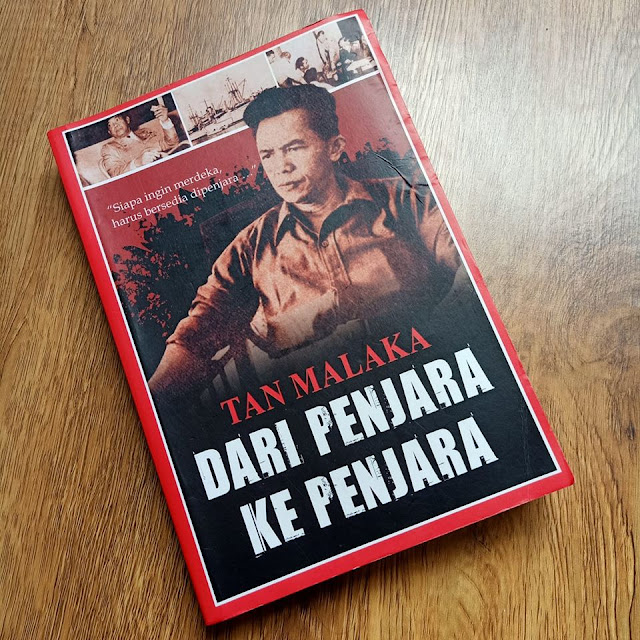
Comments
Post a Comment