Dari Penjara ke Penjara [Resensi]
Buku ini saya dapet dari cuci
gudang Gramedia beberapa waktu yang lalu. Perspektif kesejarahan setelah
membaca Bumi Manusia dan Hindia Belanda 1930, membuat saya tertarik untuk tahu
lebih banyak tentang pemikiran, sudut pandang, dan situasi kebatinan para
pelaku sejarah. Terlebih mereka-mereka yang memang include sebagai tokoh
pergerakan. Maka ketika melihat buku ini ada di tumpukan buku-buku sejarah, tak
butuh waktu lama bagi saya untuk memilih.
Pada intinya buku ini bercerita tentang
“petualangan” Tan Malaka di beberapa fase penting dalam kehidupannya. Diawali
dari cerita Tan Malaka yang melanjutkan sekolahnya di Belanda dengan beasiswa, kemudian
pulang kampung dan menjadi semacam guru bantu di sekolah anak kuli perkebunan
tembakau Deli. Beberapa waktu kemudian, ia merantau ke Semarang dan ikut
membangun sekolah rakyat di sana. Di sinilah Tan Malaka mulai intens bergerak
sebagai aktivis murba dan menjadi fungsionaris PKI saat itu. Merasa kehadiran
Tan Malaka mengganggu, Pemerintah Hindia Belanda kemudian menangkapnya dan singkat
cerita membuangnya kembali Belanda. Dari Belanda, ia memulai perjalanannya melintasi
berbagai negara, mulai dari Jerman, Rusia, Filipina, Tiongkok, Myanmar,
Malaysia, Singapura, hingga akhirnya kembali ke Indonesia setelah Hindia
Belanda menyerah kepada Jepang di awal-awal Perang Dunia II.
Perjalanan melintasi berbagai
negara inilah yang menjadi benang merah cerita dalam buku ini. Di setiap negara
yang ia lewati, Tan Malaka selalu menceritakan pandangannya terkait kondisi sosiopolitik,
sejarah perlawanan terhadap imperialisme, serta cara yang ia lakukan untuk bertahan
hidup. Tentu saja semua perjalanan itu ia lakukan dalam konteks pelarian politik.
Tan Malaka pernah beberapa kali ditangkap, kemudian kabur/dilepaskan lagi. Maka
melakukan penyamaran, berganti-ganti identitas, sampai memalsukan dokumen
administrasi sudah menjadi bagian “normal” dari kehidupannya. Karena cerita
dalam buku ini ditulis sendiri oleh Tan Malaka, maka semua cerita itu adalah
memoar yang orisinil. Membacanya seolah sedang membaca sebuah diari.
Ada beberapa hal yang saya
rangkum dan barangkali bisa menjadi pelajaran.
Pertama, Tan Malaka adalah sosok
yang luar biasa adaptif. Ia mudah belajar, mudah bergaul, dan peka terhadap
situasi di sekitarnya. Di masa-masa awal, Tan Malaka mengaku hanya bisa
berbahasa Melayu dan Belanda, namun ketika ia sadar butuh memahami bahasa Inggris
diapun berhasil mempelajarinya dalam waktu singkat bahkan menjadi sumber
penghidupan dengan menjadi pengajar bahasa tersebut. Hal yang sama juga berlaku
di tempat lain. Tak heran Tan Malaka juga akhirnya dikenal menguasai sekurang-kurangnya
bahasa Mandarin, Jerman, dan Tagalog yang terbukti sangat membantunya dalam
masa pelarian. Ia juga bisa mencium situasi ketika dirinya dalam bahaya sehingga
bisa menyusun rencana pelarian atau pembelaan diri.
Kedua, networking Tan Malaka
benar-benar ajib untuk ukuran di masa itu. Di hampir semua negara yang ia
lewati, Tan Malaka selalu punya relasi yang menjad asylum, setidaknya untuk
sementara. Sembari dirinya mencari penghidupan, ia membangun relasi baru dengan
warga lokal dan memperoleh simpati dari mereka. Pernah suatu ketika di
masa-masa krisis di Singapura, Tan Malaka berhasil meyakinkan petugas imigrasi untuk
memberikannya surat jalan, padahal surat jalan itu berasal dari negara yang
tengah memburunya. Dengan networking pula Tan Malaka selalu punya cara untuk
mencari nafkah selama masa pelarian, mulai dari menjadi juru tulis, kontributor
pers, hingga pengajar di negeri orang.
Ketiga, selama lebih dari 20
tahun masa-masa petualangan yang diceritakan, Tan Malaka menunjukkan
konsistensi atas pembelaan terhadap kaum murba (jelata). Barangkali spirit
semacam itu yang membuatnya condong terhadap sosialisme-komuniesme dan
menganggapnya sebagai antithesis dari imperialisme. Di sekolah anak kuli di
Deli, Tan Malaka menggagas ide bahwa anak kuli butuh lebih dari sekedar ilmu
tentang perkulian. Pendidikan harus ditujukan untuk mempertajam kecerdasan
(intelektual), memperkokoh kemauan (self motivation), dan memperhalus perasaan
(empati). Di sekolah rakyat Semarang, Tan Malaka juga mengganggap orientasi
pendidikan tidak boleh sebatas mengajarkan kompetensi untuk menjadi juru tulis
(profesi yang cukup beken saat itu bagi masyarakat pribumi), tapi juga harus
mengajarkan spirit entrepreneurship agar mereka kelak bisa berdikari dan bebas
untuk berjuang.
Sedikit memperpanjang di bagian
ini, satu lagi contoh yang mungkin secara jelas menggambarkan kepedulian Tan
Malaka, adalah apa yang diperbuatnya di pertambangan Bajah Kozan (sekarang Banten).
Pertambangan itu dimiliki dan dikelola oleh orang Jepang dengan mempekerjakan romusha.
Sebelumnya, di sana romusha diperlakukan ala kadarnya dan kurang dimanusiakan.
Minim bahan pangan, minim sarana kesehatan, minim bahan pakaia. Bahkan sebagian
romusha didatangkan dengan tipu muslihat. Oleh para pamong, para petani di
daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dipanggil di sawahnya diiming-imingi untuk ikut
pelatihan. Tanpa rincian informasi, tanpa bekal, bahkan tanpa informasi kepada
keluarganya para petani yang sudah berkumpul ini lantas dibawa ke Banten tanpa
tahu apa-apa. Di sana mereka dipekerjakan sebagai romusha. Mereka yang tidak
terima kemudian ada yang kabur berusaha pulang kembali. Namun karena buta huruf
dan tak punya keahlian, banyak dari mereka yang jatuh sakit dan meninggal di
perjalanan.
Singkat cerita ketika Tan Malaka
pulang ke Indonesia dan bekerja di pertambangan ini, ia pun berupaya mengubah
situasi. Saat dipercaya menduduki posisi yang mengelola romusha, ia memperbaiki
administrasi sehingga meminimalisir perilaku tipu muslihat dari para pamong.
Selain itu dia juga mendirikan dapur umum untuk menjamin ketersediaan dan
kualitas pangan, membuat bilik-bilik agar para romusha ini tidak tidur di
tanah, menginisiasi kebun sayuran sendiri supaya pasokan gizi terpenuhi, bahkan
membuat lapangan sepakbola dan pementasan sandiwara untuk sarana hiburan.
Keempat, Tan Malaka adalah pemikir
ulung. Barangkali hal itu muncul dari luasnya pembacaannya terhadap sejarah dan
filsafat. Ia bisa menjelaskan dengan baik bagaimana gerakan perlawanan rakyat
Filipina terhadap penjajah Spanyol sekaligus menganalisa mengapa tiga serangkai
yang menjadi motor perlawanan di awal, yakni Mabini, Bonifacio, dan Aquinaldo, justru
berseteru di akhir. Demikian pula penjelasannya mengenai naik turunnya gerakan
Kuomintang dan Sun Yat Sen di Tiongkok, sebab-sebab meredupnya pengaruh Kesultanan
Malaka yang dulunya digdaya, hingga bagaimana model pasar bebas mempersempit
ruang gerak bangsa Melayu di Singapura. Salah satu pemikiran Tan Malaka yang mungkin
cukup menarik adalah soal perang, yang menurutnya sebagian besar adalah soal
perebutan kuasa atas faktor produksi. Ini adalah latar yang paling dominan dari
semua peperangan, sejak zaman sebelum masehi hingga zaman kiwari. Bukan idealisme
personal. Terlepas dari kita sepakat atau tidak, pemikiran semacam ini sangat
berhaga untuk memperoleh sudut pandang alternatif.
Kelima, Tan Malaka adalah sosok vokal
dan kritis. Ini tentu sudah bukan perdebatan lagi. Tan Malaka terbiasa menulis
bahkan membuat propaganda-propaganda perlawanan. Ia tidak pernah segan
menyampaikan pemikirannya secara argumentatif. Dalam suatu pertemuan besar di
Bajah Kozan yang dihadiri oleh para petinggi dari Jepang, secara terbuka ia menyampaikan
bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah syarat untuk bisa bekerjasama secara
setara. Di lain kesempatan, Tan Malaka juga menunjukkan ketidaksetujuannya
terhadap cara Bung Karno memposisikan Jepang. Bung Karno pernah bilang bahwa
setetes keringat romusha adalah racun bagi sekutu. Bagi Tan Malaka retorika Bung
Karno ini hanya sekedar bunga-bunga yang tidak berdasar pada realita. Demikian
pula Tan Malaka juga mengkritik konsep koperasi ala Hatta yang menurutnya
secara implementasi tidak mempertimbangkan relasi kuasa. Keluputan ini menyebabkan
koperasi justru jadi media korupsi para pengurus yang lantas merugikan
anggota-anggotanya.
Saya merasa memperoleh manfaat
dari buku ini. Akan tetapi secara penulisan/penerbitan ada berbagai kekurangan.
Satu kekurangan yang cukup mengganggu adalah kesalahan ketik yang cukup
konsisten yakni kata “dari” kerapkali ditulis “dan”. Selain itu buku ini juga menggunakan
gaya kesusastraan melayu lama, sehingga pembaca yang kurang familiar barangkali
sedikit kesulitan untuk memahami beberapa bagian karena terasa seperti ada kata
atau frasa yang kurang lengkap atau berbeda SPOK-nya dengan PUEBI yang baru. Kekurangan
lainnya adalah adanya halaman yang hilang (Hal 560) yang untungnya untuk kasus
saya penerbit menempelkan halaman yang hilang itu di balik cover belakang.
Akhir kata, buku ini cukup baik
untuk menjadi tambahan referensi yang berharga bagi rekan-rekan yang menyukai
buku bergenre sejarah. Karena bukan hanya sejarah Indonesia yang kita peroleh
wawasannya, melainkan juga sekelumit sejarah di tempat-tempat yang Tan Malaka
lewati. Bagi yang menggemari persoalan filsafat dan pemikiran, buku ini juga
bagus karena memberikan pembacanya perspektif seorang yang berhaluan kiri.
Terakhir, bagi yang tertarik dengan biografi para pejuang dan pahlawan
nasional, buku ini barangkali salah satu bacaan penting karena akan banyak spirit
yang bisa diteladani dari perjalanan Tan Malaka. Tak ada perjuangan tanpa
pengorbanan, seperti kata Tan Malaka sendiri, “Siapa ingin merdeka, harus
bersedia dipenjara.” Tentu petuah ini tidak harus kita maknai secara
letterlijk. Namun setidaknya kita paham bahwa semakin bernilai sesuatu, semakin
mahal pula harga yang harus kita bayar. Dan semakin tinggi hasil yang kita
ingini semakin besar pula risiko yang perlu kita hadapi.
Wallohua’lam
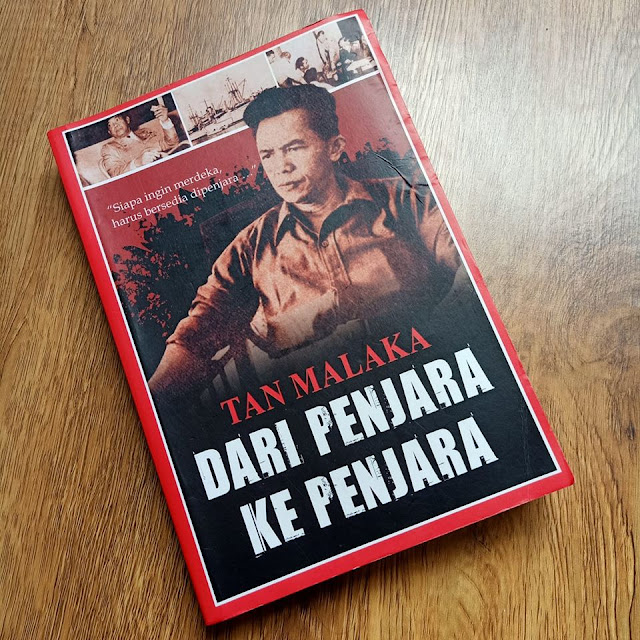
Sepertinya akan menarik kalau resensi ini memiliki judul.
ReplyDelete