FPI Hendak Dibubarkan, Apa Sikap Kita?
Belakangan ini muncul banyak aksi
penolakan warga terhadap FPI. Penolakan itu didasarkan pada kiprah FPI yang
terlihat cenderung kasar dan main hakim sendiri. Ini patut disayangkan karena
FPI pada prakteknya bukanlah ormas biasa. FPI adalah ormas yang bernafas Islam,
yang seharusnya kehadirannya bisa disambut baik oleh ummat yang notabene juga
mayoritas islam. Jika keadaan menunjukkan adanya penentangan dari sebagian
masyarakat Islam terhadap sebuah ormas islam, maka ini mengindikasikan ada
sesuatu yang salah di sini. What’s wrong?
Saya kira sikap bijak kita adalah
tidak menempatkan permasalahan dalam konteks hitam putih. Ini bukan soal siapa
(who) yang salah dan siapa yang benar, karena kalaulah yang disorot itu
subjeknya, yang salah belum tentu 100% salah dan yang benar pun belum tentu
100% benar. Masalah harus ditempatkan secara jernih, objektif, dan to the point
tentang apa titik yang menjadi inti persoalan. Dalam hal ini, tentu saja
kekerasan.
Dalam wacana umum, kekerasan
selalu berkonotasi negatif. Terkecuali pada kondisi yang amat khusus seperti
membela diri dan sebagainya. Yang menjadi sorotan para penolak adalah sisi
kekerasan yang ditunjukkan FPI. Pengrusakan fasilitas publik dan perkelahian
adalah contoh kekerasan itu. Yang patut kita pertanyakan dan telusuri lebih
lanjut adalah benarkah kerja FPI “hanya” melakukan kekerasan? Selama ini memang
kita akui yang aktif disorot oleh media hanyalah sisi kekerasannya. Media
jarang atau bahkan tidak pernah meyorot aksi-aksi damai yang dilakukan FPI,
seperti penggalangan dana untuk korban gempa, pengajian, dialog akademis, dan
sejenisnya. Kalaupun memang kekerasan yang terjadi terbukti dilakukan oleh
oknum FPI, sejauh apa asbabul wurud terjadinya kekerasan seperti itu? Dari
semua aktivitas FPI di Indonesia, berapa persen yang berakhir ricuh dengan
kekerasan? Apakah persentase itu kemudian sudah sampai pada taraf yang bisa
mengkonfirmasi statemen bahwa “Dominan aktivitas FPI adalah kekerasan”?
Saya secara pribadi menolak jalur
kekerasan dalam penyelesaian masalah. Bagi saya, yang berwenang melakukan
tindakan koersif adalah penyelenggara negara berdasarkan aturan yang berlaku.
Kekerasan bukan wewenang individu, ormas, parpol, LSM, maupun badan lainnya di
luar negara. Namun itu berlaku apabila negara memang melakukan tugasnya dengan
baik. Bila negara lalai dari tanggungjawab ini, di mana aturan yang ditetapkan
dilanggar sendiri (dalam perizinan judi dan pelacuran misalnya), maka munculnya
vigilante pun sedikit banyak bisa
dimengerti. Jika di roman bangsa Inggris pernah ada Robin Hood, di cerita
rakyat Meksiko ada Zorro, dan di cerita epik Tiongkok ada gerombolan bandit
Ryuzanpaku, maka sebutlah di Indonesia ada Front Pembela Islam. Bukan bermaksud
membela tindakan kekerasan, hanya sekedar mengingatkan bahwa kekerasan di sini
seringkali tak datang begitu saja dari ruang hampa.
Jangan lupa pula bahwa tak
sedikit anggota masyarakat yang seringkali merasa sudah tahu segalanya hanya
dengan menerima kabar dari media. Era keterbukaan informasi seperti sekarang
ini memang meniscayakan seseorang mengakses informasi tentang apa saja. Tapi
masalahnya, tidak semua informasi yang beredar itu benar, akurat, dan lengkap.
Sehingga pengambilan kesimpulan yang terlalu dini berarti tak ubahnya menyikapi
sesuatu secara subjektif, bukan objektif. Inilah yang akhirnya menjadi sorotan.
Pertama, sejauh apa kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan berita tentang sepak
terjang FPI selama ini di masyarakat? Kedua, apakah penolakan-penolakan itu
murni aspirasi masyarakat atau memang sengaja intrik pihak-pihak tertentu yang
selama ini gerah dengan aktivitas FPI? Itulah sebabnya sikap sabar dibutuhkan
dalam merespon hal seperti ini karena itu semua butuh kajian yang mendalam.
Kemudian persoalan pun sebenarnya
tidak akan berhenti pada pembubaran saja. Kalaupun sebuah ormas dibubarkan, ia
bisa hadir kembali dalam bentuk baru namun dengan format lama. Jika dibubarkan
lagi maka ia tinggal membentuk lagi. Begitu seterusnya. Mirip dengan tokoh Bhu
di film Dragonball Z. Sehingga wacana pembubaran pun akan kurang relevansinya
tanpa follow up. Follow up yang saya maksud di sini adalah kegiatan untuk
merekonstruksi kembali paradigma baru dalam bersikap. Yakni paradigma ud’u bil hikmah wal mau’idzotil hasanah,
paradigma damai dan non kekerasan. Ini tidak hanya mencakup ormas yang hendak
dibubarkan, tapi juga pemerintah sebagai penyelenggara negara. Sebuah ormas
bisa saja digembleng untuk tidak main hakim sendiri, tapi itu meaningless tanpa komitmen aparat untuk
memberikan penghakiman secara benar. Yang ada nantinya malah lingkaran setan
yang terus menerus berputar tanpa akhir.
Inilah potret bangsa kita saat
ini. Bagaimana potret bangsa kita di masa depan, tak ada yang tahu. Tapi saya
kira kisi-kisi jawabannya bisa kita lihat dari bagaiman kita menyikapi berita
ini. Apakah kita termasuk orang yang latah pada opini kerumunan? Ataukah
termasuk orang yang kritis dan cermat menyikapi persoalan? Jawabannya
tergantung pilihan kita sendiri.
Wallohua’lam
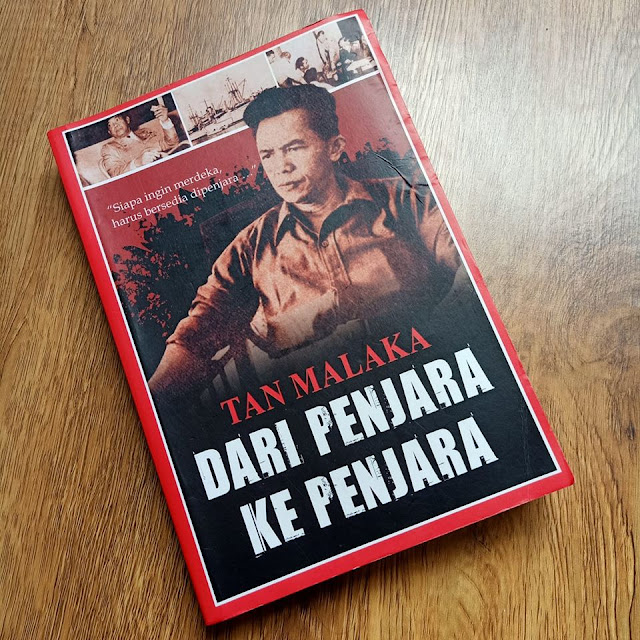
Comments
Post a Comment