Mengapa Saya Berhenti Liqo? (I)
Saya termasuk orang yang
beruntung pernah kuliah di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.
Bukan hanya karena almamater saya punya integritas akademik, tapi juga karena
kondisi pendidikannya yang cukup kondusif untuk pengembangan diri, salah satunya
adalah pengembangan diri di bidang kerohanian. Mentoring (istilah yang kemudian
berevolusi menjadi liqo -bertemu, bhs. arab), adalah aktivitas yang
cukup populer di sana. Dimotori oleh LDK (Lembaga Dakwah Kampus), mentoring
menjadi semacam primadona kegiatan yang gencar disebarluaskan, bahkan sejak
pertama kali mahasiswa baru menjejakkan kakinya di kampus tersebut.
Secara khusus, mentoring yang
dibahas di sini adalah aktivitas pengembangan diri di bidang keislaman yang
dipandu oleh seorang mentor (murobi) dalam sebuah kelompok beranggotakan 5-12
orang. Agendanya beragam, dari mulai membaca al Qur’an secara bergiliran,
tausiyah (pemberian nasehat), cek n ricek ibadah harian, musyawarah tentang
sesuatu, bedah buku, mengakaji siroh/sejarah Nabi dan sahabatnya, hingga curhat
problematika hidup yang dihadapi. Di akhir, selalu ditutup oleh doa rabithah.
Dengan agenda seperti ini, banyak mahasiswa (terlebih yang punya ghirah
keislaman yang tinggi) yang tertarik untuk ikut di dalamnya.
So what is the problem anyway? Bukankah itu semua bagus? Ya, tentu
saja jika memang kondisinya hanya sebatas itu. Di beberapa tulisan saya
terdahulu, saya pernah sedikit memaparkan bahwa ada hal yang menjadi kekurangan
sistem dakwah kampus. Beberapa kekurangan yang saya dan sebagian orang rasakan
adalah eksklusifnya sistem yang melingkupi aktivitas mentoring tersebut.
Mentoring, pada gilirannya menjadi semacam parameter umum untuk menentukan ‘kualitas’
seseorang di mata para aktivis dakwah kampus. Gampangnya, orang yang mentoring
berarti ‘kualitas’nya di atas orang yang tidak mentoring. Mengapa saya
berkesimpulan seperti itu? Dulu saya cukup sering mendengar pertanyaan seorang
rekan pada saya tentang seseorang, “Akhi, dia itu mentoring kagak?” Jika
seseorang itu ikut mentoring, maka biasanya ia diberi dukungan untuk ikut dalam
sebuah kelembagaan mahasiswa, lomba-lomba, atau ajang-ajang bergengsi lainnya. Lalu
apakah orang yang tidak mentoring tidak didukung? Dalam beberapa hal mereka
juga mungkin didukung, tapi tentu tidak sebanyak jika mereka ikut mentoring. Kesimpulannya,
mentoring ternyata dijadikan semacam alat untuk polarisasi orang-orang.
Efek dari polarisasi mentoring-tidak
mentoring itu bagi saya adalah sikap diskriminasi. Mirip politik apartheid di
Afrika Selatan dulu. Yang mentoring ibarat masyarakat kulit putih, sedangkan
yang tidak metoring ibarat masyarakat kulit hitam. Kulit putih selalu punya
akses yang lebih banyak ketimbang kulit hitam.
Saya sebenarnya pernah mencoba
meminta klarifikasi ini dari beberapa orang yang saya anggap punya pengaruh
dalam sistem seperti itu. Bagi mereka, itu sah dan wajar-wajar saja, karena
dengan mentoring orang-orang setidaknya punya standar bersama tentang akhlak
dan pemikiran. Orang yang ikut mentoring bisa lebih terpantau perilakunya,
kebiasaannya, dan gerak-geriknya ketimbang yang tidak. Jadi logikanya, mereka
didukung karena ikut mentoring lebih memberikan kepastian (bahwa mereka cukup
baik) ketimbang yang tidak. Namun jawaban mereka sebenarnya belum memuaskan
hati saya. Sepintas, logika itu ada benarnya, tapi bagi saya logika seperti itu
makin terkesan menganggap wajar sebuah diskriminasi dan standar ganda. Bukan
hanya karena perihal keikutsertaan di mentoring adalah hal yang terlalu sempit
untuk menilai seseorang, tapi lebih dari itu sikap seperti itu justru seperti
sikap menutup mata pada potensi orang lain (baca: meremehkan orang lain).
Sebutlah misalnya, dalam rekrutmen sebuah organisasi dakwah fakultas, ada sosok
A yang kapabilitasnya cukup baik di mana
ia ikut mentoring dan sosok B yang kapabilitasnya jauh lebih baik tapi ia tidak
ikut mentoring. Kenyataan di masa saya dulu, A lah yang lebih diprioritaskan
ketimbang B. Lucu bukan?
Itulah yang kemudian membuat
saya berpikir, entah benar entah tidak, bahwa sistem seperti itu cenderung
tidak toleran pada perbedaan pemikiran. Mentoring dijadikan kerangka untuk
memastikan bahwa pemikiran seseorang sama (atau setidaknya cenderung sama) dengan
pemikiran yang diadopsi oleh sistem. Dalam beberapa kasus, itu memang bisa
diterima karena ada hal-hal di mana kesamaan pemikiran menjadi syarat
berjalannya sesuatu. Di Parpol misalnya. Tapi malangnya, itu terjadi di semua
lini, tidak hanya lini-lini tertentu.
Saya pernah punya pengalaman
menarik. Sejak awal mengikuti mata kuliah PAI (Pendidikan Agama Islam) di
semester awal, saya sudah berangan-angan menjadi seorang asisten PAI. Di kampus
saya dulu, PAI punya 3 SKS sehingga selain kuliah, ada juga aktivitas
responsinya, dan responsi itu dipandu oleh seorang asisten. Lalu bagaimana
sistem responsinya? Yup, tepat! Bentuk responsinya adalah mentoring. Saya punya
keinginan untuk menjadi asisten PAI di tingkat atas nanti.
Tahun berikutnya saya pun mulai
mencari2 di mana kiranya bisa mendaftar seleksi asisten PAI itu. Infonya tidak
ketemu, dan tiba-tiba saya dikejutkan oleh pengumuman di mading masjid, bahwa
calon asisten dipersilakan untuk ikut tes hari ini jam segini di sini. Tentu
nama saya tidak ada di sana. Saya pun bersabar dan berprasangka baik, mungkin
saya saja yang ketinggalan berita. Tahun berikutnya saya coba lagi, tapi info2
pun tak kunjung saya dapatkan. Entah memang karena saya kurang mencari atau
karena memang infonya ditutup-tutupi saya tidak tahu. Tapi pengumuman di mading
masjid lagi-lagi mengejutkan saya. Ada daftar calon asisten di sana (tentu nama
saya tidak ada) beserta jadwal tes dan tempat tesnya dilaksanakan. Beruntung
ada salah seorang teman saya yang tercantum namanya di mading. Saya lalu
konfirm ke beliau, daftarnya di mana dan bagaimana caranya. Tapi jawabannya
lebih mengejutkan hati saya. Ia ternyata tidak mendaftar sama sekali, dan tak
tahu menahu tentang pencantuman namanya di mading. Yang ia ingat, mentornya
(murobinya) memang pernah merekomendasikannya untuk jadi asisten, dan ia pun
setuju. Hanya itu. Tak ada administrasi sama sekali yang dilewatinya. Dan
akhirnya ia pun ikut formalitas tes dan menjadi asisten PAI.
Nah, ternyata, sebegitu kuatnya
peran mentoring. Bahwa keikutsertaan seseorang justru sangat dipengaruhi oleh
rekomendasi mentor atau murobinya. Di kasus di atas, masalahnya sebenarnya
bukan pada apakah saya jadi asisten PAI atau tidak, tapi pada ketidakmerataan
akses untuk beramal, berkontribusi menjadi asisten PAI. Padahal, mata kuliah
PAI adalah mata kuliah resmi di kampus saya, hanya saja pengelolaannya memang diurus
oleh pihak masjid. Pada saat itu saya sebenarnya juga ikut mentoring, namun mentoring
yang saya ikuti memang ada dua: satu metoring yang dikelola masjid kampus, dan
satu lagi mentoring yang dikelola badan kerohanian islam kampus. Belakangan
baru saya tahu bahwa mentor/murobi saya tidak merekomendasikan saya untuk jadi
murobi hanya karena saya ikut dua mentoring tersebut. Apakah karena di
mentoring yang satu lagi itu dianggap sesat sehingga takut terinfiltrasi
pemikirannya, saya kurang tahu. Wallohua’lam.
(bersambung ke Mengapa Saya Berhenti Liqo? (II))
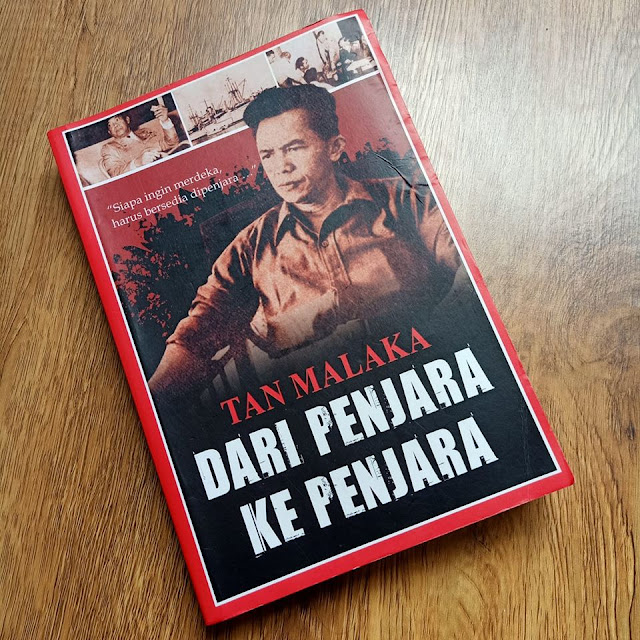
sedikit mewakili pemikiran an bang,, tapi sejauh ini an belum berani berbicara karena pemahaman yang dangkal,, insyaAllah terus belajar,, dan bekal dari ppsdms alhamdulillah meminta kita menempatkan diri pada posisi yang bijak dengan open mind, rendah hati dan objektif" overall ini harusnya juga jadi bahan pertimbangan sistem kampus dalam pengambilan setiap keputusan,, pandangan orang2 di luar sistem tentunya akan meluaskan pola pandang pengambil kebijakan,, syukron tulisannya bang..
ReplyDeleteYup...teruslah kita belajar n tetap menjaga objektivitas, open mind, dan sikap rendah hati. Sama2 ya Bang Sigit, makasih juga buar responnya
ReplyDeletesaya pikir, ini hanya ada dalam pikiran saya (sejak TpB)..Eh disini malah dijelaskan gamblang. saya ikut sana, ikut sini, ikut A ikut B..tapi sampai wisuda yang saya pegang pemahaman islam yg di dapat di kampung waktu belajar di TPQ :)
ReplyDeleteternyata sama,,,,,,,,,,,,,,,
ReplyDeleteSistem seperti yang ente ceritakan itulah yang sebenarnya bisa menghancurkan Nilai-Nilai Kepemimpinan dalam Islam.
ReplyDeleteDan lebih mirip Nepotisme, karena hanya untuk golongannya.
Keseluruhan saya setuju dengan artikel ini.
menjurus ke arah 'pengendalian/kjontrol'. dan ini bisa dimaklumi karena akhir dari gerakan parameternya adalah politik. sebenarnya ga masalah asal sadar posisi. namun jika gennya bukan orpol ya jangan disitu hehe
ReplyDeleteSependafat kak
DeleteWah sama kayak ana waktu SMA , kalau ikut ROHIS pasti gampang masuk kejajaran OSIS dan MPK, dan itu terbukti ana ikut ROHIS dari awal, tapi ada orang yang baru masuk ROHIS akhirnya masuk ke jajaran OSIS/MPK juga.
ReplyDeleteMakanya ana juga malas ikut Liqo2an lagi sejak lulus dari SMA.
Salam Muhammadiyah.
ga ada yang salah sih dengan niat belajarnya di sistem itu,. cuma gw suka sudut pandang yang ini to,. realita sekali,. udah banyak pola kultur yang ga relevan lagi saat ini tapi masih diwariskan,. semoga tulisannya menginspirasi tmn2 yg masih punya kesempatan untuk ambil bagian dari perubahan,.
ReplyDeleteYang penting konsisten ibadah kepada Allah SWT. Allah yang membuat seseorang bisa maju atau mundur. Kedekatan pada Allah-lah kunci segalanya. Bukan dekat dengan orang ini atau orang itu. Tetap dekati Allah Akh. Dekat dengan Allah. Hidayah itu harus kita kejar. Semoga kita tetap dekat dengan Allah. Semoga Allah selalu menjaga antum dan kita semua. Aamiin
ReplyDelete'Politik'nya kuat sekali
ReplyDeletekamu coba luruskan niat. beberapa orang liqo hanya karena merasa kesulitan untuk membina imannya. beruntunglah mereka yang liqo ada "yang mau" membina mereka. luruskan niat. ikut liqo untuk memperbaiki diri. udah jangan pikirin yang lain
ReplyDeleteSependafat kak
DeleteItu semua bertujuan untuk doktrinisasi. Karena kalau orang yang sudah ikut pengajian lain dikhawatirkan akan membuat membongkar cara-cara dokrinisasinya.
ReplyDeletebaca ini dan juga komennya.
http://ustadzaris.com/pengajian-sembunyi-sembunyi-tanda-kesesatan/comment-page-1#comments
Setahu saya tidak semua seperti itu. Dan wajar sih itu pemikiran antum. Tapi alangkah baiknya jika tidak hanya melihat dari kejadian yang ada dikampus antum saja bisa juga dilihat dari sistem mereka bagaimana, dikampus lain bagaimana. Karena sebenarnya sistem itu sudah bagus.. hanya orang didalamnya yang terkadang membuat sistem itu justru terlihat jelek. Dan ada baiknya antum sebagai sesama muslim jika ingin mengkritik langsung ke orang nya atau pengurusnya bukan di umum. Karena apa yang orang lain tau, belum tentu antum tau. Begitu pun sebaliknya. Wallahu a'lam.
ReplyDeleteSalam ahlussunah
bentar deh.. untung saya baca beberapa artikel.. g cuma artikel ttg "Berhenti Liqo" tp jg beberapa artikel terbaru
ReplyDeletehehe
jd g salah paham sama Mas
Yuk perbanyak literasi . Biar gak #gagal_paham.
ReplyDeleteSaya mengira sebelumnya, bahwa hanya saya saja yg merasa berpikiran seperti ini.
ReplyDeleteTulisan di atas sedikitnya mewakili apa yang menjadi pikiran saya selama ini
Izin share ustad
ReplyDelete