Fikih Nawazil [Resensi]
Nawazil dalam bahasa arab adalah bentuk jamak dari kata nazilah. Kata yang sama dengan yang ada di belakang kata ‘qunut nazilah’. Secara istilah, nazilah diartikan peristiwa atau persoalan baru yang muncul. Ketika disandingkan dengan kata fikih di depannya, maka dia bermakna fikih yang terkait dengan upaya penjabaran hukum dari peristiwa-peristiwa dan persoalan baru. Dalam bahasa sederhana, fikih nazilah adalah fikih kontemporer.
Buku ini membahas banyak persoalan, diantaranya keniscayaan ijtihad dalam merespon hal-hal baru, bagaimana kaidah-kaidah berijtihad, apa saja hal-hal yang harus jadi pertimbangan pada saat berijtihad, seperti apa ketentuan dalam memilih madzhab, bagaimana berinteraksi dengan perbedaan pendapat para ulama, apakah boleh sengaja mencari-cari pendapat yang meringankan (rukhshah) dari suatu persoalan, dan sebagainya. Bagi saya bahasan-bahasan ini semuanya menarik. Temanya relevan di tengah bermacam ragamnya pemikiran keislaman seiring dengan merebaknya kajian-kajian digital di internet. Setidaknya jabaran dari buku ini sedikit banyak bisa memandu seperti apa kita, saya khususnya sebagai awam, harus bersikap.
Saya mulai dari yang jeleknya dulu. Yang saya tidak sukai dari buku ini adalah kualitas terjemahannya yang tidak terlalu baik. Ketika menjelaskan yang sifatnya kaidah atau konsep, ada banyak yang kalimat-kalimatnya membingungkan. Barangkali karena terjemahannya langsung disadur kata demi kata dari bahasa arab, bukan dari interpretasi kalimatnya. Jadi untuk memahaminya, saya tidak bisa menggunakan teknik membaca cepat seperti di buku-buku sebelumnya. Saya perlu mengambil jeda beberapa waktu, mencerna pelan-pelan, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan maksudnya. Itupun belum membuat saya bisa menyerap 100% bahasannya. Untuk menggenapinya barangkali perlu pembacaan ulang di lain waktu.
Namun demikian, setidaknya saya tetap bisa menangkap inti dari masing-masing bahasannya. Inti yang saya pandang cukup penting ada beberapa, diantaranya:
Pertama, sebuah fatwa yang baik membutuhkan analisa yang benar-benar cermat dan hati-hati. Seorang mufti (pemberi fatwa) harus paham betul konteks dan membatasi obyek yang dia berikan fatwa. Jadi sebuah fatwa sesungguhnya sangat situasional sifatnya. Ketika konteksnya berubah, atau batas obyek fatwa terlampaui, maka fatwa tidak lagi berlaku dan dibutuhkan fatwa baru.
Kedua, perbedaan pendapat (khilaf) para ulama sangat banyak sekali terjadi. Hampir di setiap bahasan, selalu saja ada pro kontra para ulama atas suatu hal. Dari mulai boleh tidaknya seseorang bermazhab selain mazhab yang empat, boleh tidaknya kiyas dipakai untuk persoalan di luar masalah keduniaan, boleh tidaknya seseorang sengaja mencari pendapat ulama yang meringankan, sampai perbedaan cakupan sah atau tidaknya beberapa ibadah. Bahkan ada perbedaan yang kalau orang awam di kita mengetahuinya, barangkali akan menganggapnya pendapat yang nyeleneh. Saking banyaknya perbedaan itu, saya sendiri kalau diminta untuk menyimpulkan jadi agak kesulitan. Pelajarannya, dari perbedaan itu semua kita didorong untuk bersikap tasamuh (bertoleransi) tanpa harus melepaskan diri dari keyakinan atas kebenaran pendapat yang kita pegang.
Ketiga, Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat tengahan, moderat, dan seimbang. Ini terlihat dari banyak sekali sisi. Misalnya kita didorong untuk bersikap hati-hati terhadap sesuatu yang sifatnya masih samar (syubhat). Kalau sesuatu yang samar itu ada kemungkinan merupakan hal yang haram atau membuat sebuah amal ibadah menjadi tidak sah, lebih baik dia dihindari sejak awal. Akan tetapi sikap terlalu hati-hati juga tercela apabila sampai menyebabkan kita jatuh dalam bahaya, atau kehilangan maslahat yang lebih besar. Contoh lainnya, adalah anjuran Islam agar mufti mengedepankan sikap taisir (memberi kemudahan). Karena prinsip ini, jenis najis tertentu bisa berubah statusnya apabila dalam suatu kondisi dia sulit dihindarkan, atau sebuah standar bisa ditetapkan untuk menjadi batasan kebolehan sebuah transaksi meskipun di zaman Nabi standar itu tidak ada. Ini semua hanya demi memudahkan umat. Namun demikian, sikap taisir tersebut tetap harus berada dalam koridor sehingga tidak jatuh ke sikap abai dan meremehkan.
Disamping tiga inti di atas, ada banyak lagi manfaat yang bisa dipetik dari buku ini. Antara lain beberapa wawasan fikih, terutama terkait beberapa kaidah dalam menyimpulkan suatu hukum. Wawasan ini tentu saja tidak akan cukup untuk membuat pembacanya menjadi ahli fikih, tapi setidaknya dia cukup membantu untuk memahami latar belakang dan cara kerja bagaimana suatu fatwa itu bisa muncul ke masyarakat, dengan kasimpulan yang kadang tidak sama.
Ditulis oleh Lembaga Darul Ifta Mesir, buku setebal 314 halaman ini sepertinya memang bukan buku populis. Agar bisa membacanya secara baik, si pembaca perlu menguasai beberapa terminologi fikih sebelumnya mengingat ada banyak sekali jargon-jargon fikih yang digunakan di buku ini. Bisa jadi ini juga alasan kenapa saya belum bisa 100% menangkap isi buku selain terjemahan yang kadang membingungkan. Meski demikian, bukan berarti orang awam dilarang untuk membacanya. Dengan kesediaan mengeluarkan effort lebih, saya malah berpikir orang awamlah yang akan menerima manfaat paling besar dari buku ini. Karena dengannya mereka akan diperkenalkan dengan konsep-konsep dan kaidah penalaran fikih, yang membuat Islam menjadi agama yang selalu relevan dan responsf terhadap perubahan zaman.
Wallohua’lam.

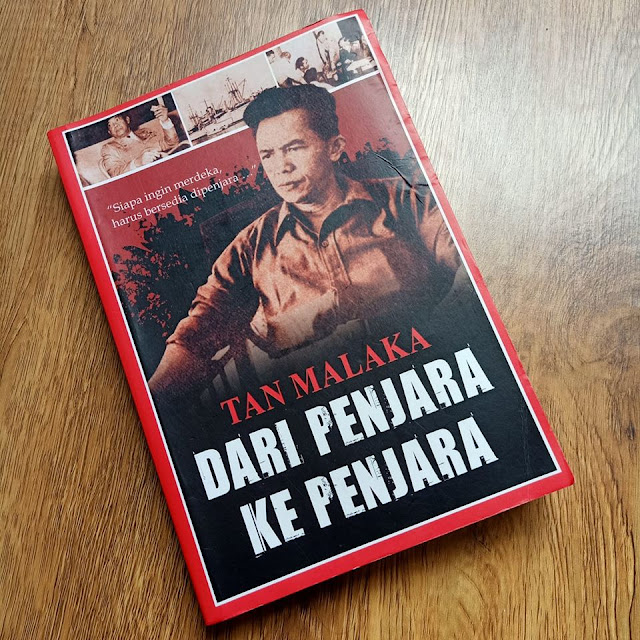
Comments
Post a Comment