Menyoal Cara Kita Berpenampilan
“Penampilan itu bukanlah yang utama, tapi yang pertama...”
Hal yang sering dikatakan orang saat melakukan penilaian terhadap orang lain adalah, “jangan lihat orang dari kulit luarnya, tapi lihatlah dalam hatinya...”, begitu kira-kira. Pernyataan tersebut seringkali diperkuat dengan beberapa fakta yang terjadi di lapangan. Banyak kasus penipuan ternyata dilakukan oleh orang-orang yang secara fisik, tampil baik, alim, dan sholeh. Dalam hal ini penampilan dijadikan alat untuk meredam kecurigaan psikologis calon korban. Contoh yang lain, banyak yang tidak menyangka bahwa bupati sebuah kabupaten di Sumatera Utara ternyata orang yang kesehariannya tampil sederhana dan selalu membawa sendiri mobilnya. Tak jarang, bupati tersebut disangka sebagai sopir Bupati!
Namun demikian, ada perihal kontraproduktif yang pada akhirnya muncul dari anggapan yang tidak proporsional terhadap pernyataan di atas. Kasus-kasus tersebut seringkali malah dijadikan sebagai alat legitimasi bagi sebagian orang yang menolak “meninjau” kembali penampilannya. Tidak sedikit juga orang yang menggunakan pernyataan di atas untuk memunculkan sinisme terhadap orang-orang yang menganggap serius perihal bagaimana tampil di muka umum.
Berbicara mengenai penampilan, maka hal utama yang tentu terkait dengan itu adalah tentang cara seseorang berpakaian. Pakaian menjadi atribut utama dalam penampilan dan semua orang setuju akan hal itu. Mode rambut dan atribut fisik lainnya menjadi urutan ke sekian setelah perkara pilihan pakaian terselesaikan. Pakaian bahkan menjadi semacam identitas diri yang pertama kali dikenal oleh publik. Tak heran jika kemudian semua suku, kebudayaan, dan agama di dunia memiliki seperangkat norma yang terkait dengan bagaimana seseorang seharusnya berpakaian secara layak.
Islam sendiri sebagai agama memiliki koridor yang membimbing pemeluknya dalam hal berpakaian serta berpenampilan. Selain sebagai identitas, pakaian memiliki fungsi perlindungan dan estetika bagi pemakainya, dan dalam Islam hal tersebut tidaklah diabaikan. Anjuran Alloh pada ummat-Nya untuk menggunakan pakaian yang bagus ketika memasuki masjid (QS 7: 31) cukup menjadi bukti akan hal ini. Di sisi lain, pakaian juga memiliki dimensi etika di mana setiap pakaian selayaknya memenuhi fungsi penutup malu disamping penutup aurat.
Menurut Anthony Robbins, seorang pakar training pengembangan diri, kondisi fisiologi termasuk pakaian yang kita kenakan secara sadar, dapat mempengaruhi sistem internal communication yang selanjutnya mempengaruhi kondisi psikologis. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Aris Ahmad Jaya, bahwa penampilan –termasuk cara berpakaian, memiliki andil dalam membangun sugesti manusia. Gejala tersebut dapat diamati dan dibuktikan pada anak-anak yang dibina oleh lembaga pendidikan nonformal seperti Birena Al Hurriyyah ataupun ProKA. Anak-anak yang mengenakan pakaian “bebas” cenderung berprilaku bebas ketimbang anak-anak yang mengenakan pakaian “cantik” seperti koko ataupun kemeja panjang.
Hal di atas bukanlah berarti bahwa merubah manusia semata-mata bisa dilakukan hanya dengan merubah penampilannya. Namun setidaknya terdapat korelasi yang cukup jelas antara penampilan fisik dengan faktor psikologis manusia. Dengan demikian, adanya koridor-koridor tertentu mengenai tata cara berpakaian dan berpenampilan tentunya sangat relevan untuk sebuah pranata dasar sosial seperti agama. Begitu pula dengan adat, serta norma-norma lain yang diakui masyarakat.
Gejala yang akhir-akhir ini dapat dengan mudah kita jumpai adalah pergeseran paradigma berpenampilan. Bisa jadi karena derasnya arus informasi dari segala penjuru dunia, yang notabene memiliki beragam sistem norma, paradigma masyarakat berpenampilan juga mengalami asimilasi. Bagi sebuah peradaban yang membuka dirinya dengan pihak lain, model asimilasi seperti itu tentunya merupakan sebuah keniscayaan. Namun hal tersebut bukan berarti tidak ada masalah dan semua hal tetap baik-baik saja. Asimilasi tersebut ternyata memiliki kecenderungan untuk berkiblat ke arah tertentu alih-alih kecenderungan progresif untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Dampaknya, akar budaya bangsa ini perlahan-lahan tercerabut dari bumi tempatnya berpijak. Asimilasi yang terjadi bukannya menyuburkan tetapi malah melayukan.
Adapun budaya yang dimaksud melayukan adalah paradigma hedonisme yang tentunya tidak bisa beriringan dengan budaya agamis yang sempat dimiliki bangsa ini. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa pola penampilan masyarakat semakin menjauh dari budaya agamis. Ketika liberalisme dan sekulerisme melanda dunia Barat, semangat revolusi hadir untuk membangkitkan renaisance yang pada akhirnya menjadi cikal bakal kemajuan mereka hingga kini. Namun ironisnya, banyak masyarakat dunia ketiga –termasuk kita, yang belum sanggup membedakan ranaisance yang berada dalam ranah teknologi dengan liberalisasi serta sekulerisasi yang berada dalam ranah ideologi. Pada akhirnya, teorema kemajuan dunia barat diadaptasikan secara bulat hingga pada tataran akhlak –termasuk tata cara berpakaian serta berpenampilan, yang sebenarnya tidak ada hubungannya lagi dengan kemajuan itu sendiri.
Kita bisa dengan mudah melihat proyeksi peradaban Barat melalui tampilan para tokoh superheronya, yang notabene dikonsumsi anak-anak. Hampir semua tokoh superhero ditampilkan dengan busana ketat serta menonjolkan sisi maskulin atau fe-mini-mnya. Padahal secara akal sehat, hal itu terkesan tidak logis karena sosok yang aktivitas sehari-harinya adalah ‘perkelahian’ tentunya membutuhkan kostum yang mampu melindungi seperti halnya baju besi Robocop, Iron Man, atau setidaknya rompi pelindung khas Shinobi Konoha. Ironisnya, model pakaian aneh ala superhero seperti itulah yang cenderung dikonsumsi.
Lalu pertanyaan utama yang kemudian pantas diajukan adalah, apakah ada yang salah dengan mengikuti pakaian seperti itu? Kita tentu saja tidak sedang berbicara dalam konteks apakah kita itu superhero atau tidak, tetapi dalam konteks norma yang berlaku di masyakat yang (katanya) agamis seperti Indonesia. Pakaian ketat, mini, dan penonjolan sisi-sisi maskulin ataupun feminim yang berorientasi sensualitas tentu bukan menjadi bagian dari keseharian umum masyarakat agamis. Sebaliknya itu adalah kebiasaan kaum hedonis. Sangat banyak norma tak tertulis terkait hal itu. Dalam skala norma yang lebih universal seperti agama, Islam menganggap menampilkan aurat (baik berupa wujud dan bentuk) ataupun sensualitas di hadapan umum sebagai sebuah hal yang tercela. Kata kuncinya adalah di hadapan umum. Apabila pakaian atau penampilan seperti itu ditampilkan dalam lingkungan terbatas untuk diri pribadi ataupun orang yang masih ‘berhak’ tentu tidak dilarang. Lingkungan terbatas itulah yang baru pantas dikatakan sebagai ruang privat dan layak dihormati. Namun apabila publik secara umum bisa mengaksesnya, penghormatan terhadap ruang privat seperti itu pun tidak berlaku lagi.
Selanjutnya, tidak sedikit orang yang berdalih dengan pertanyaan, “mana yang lebih baik antara orang yang penampilannya baik tapi kelakuannya buruk atau orang yang penampilannya tidak terlalu baik tapi kelakuannya baik?”. Jawabannya tentu adalah orang yang berpenampilan baik dan kelakuannya baik. Hal tersebut karena dunia ini tidak akan pernah hanya terdiri dari dua alternatif itu saja sehingga menjadikan dua kondisi tersebut an sich sebagai dalih tentunya bukanlah hal yang relevan untuk dilakukan.
Pada akhirnya, tulisan ini tidak ditujukan untuk mewacanakan penampilan sebagai faktor utama penilaian. Ada banyak faktor yang menyusun nilai seorang manusia. Namun, penampilan dapat dipandang sebagai perkara penting dalam diri kita karena sesungguhnya ia mewakili citra umum diri kita beserta nilai-nilai yang kita anut dan yakini, yang menjadi bagian signifikan yang menentukan siapa diri kita.
Wallohua’lam bishowab
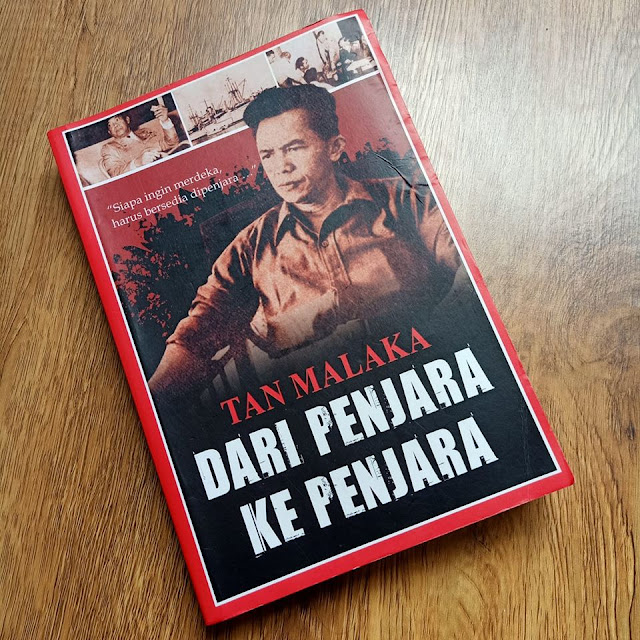
Comments
Post a Comment