Bumi Manusia [Resensi]
Ketidakadilan itu bisa merampas hal yang paling berharga dari kita, dengan cara yang tak berperikemanusiaan.
Mungkin itu kesan yang saya peroleh seusai menuntaskan novel ini.
Sejujurnya saya memang agak ketinggalan. Salah seorang teman yang anak bahasa bilang, ini bacaan mahasiswa di semester pertama. Teman seasrama dulu malah sudah punya kumpulan tetraloginya. Dan begitupula mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah membaca lebih dulu. Tapi untungnya tak ada istilah kadaluarsa untuk sebuah karya besar. Novel Pramoedya ini salah satunya.
Bagi teman-teman yang belum baca atau nonton filmnya, novel ini bercerita tentang sosok Minke, seorang Bangsawan Pribumi Jawa, yang menjalin kisah kasih dengan seorang Indo bernama Annelies. Hubungan mereka bisa dikatakan rumit karena berhadapan dengan kultur yang serba kontradiktif. Ibunya Annelies adalah seorang “gundik”, dengan segala stigma negatifnya (yang Minke sadari berbeda dengan kenyataannya). Annelies sendiri malah lebih suka dianggap pribumi meskipun situasi memberikan privilege sangat besar bagi bangsa Eropa dan Indo saat itu. Di sisi lain sosok Minke juga kerap merasakan konflik batin di tengah posisinya sebagai murid yang menerima didikan Belanda, dengan ekspektasi lingkungannya terhadap layaknya kaum priayi Jawa. Pada puncaknya, hubungan mereka berhadapan dengan perlakuan hukum yang tidak setara, yang bermuasal pada perbedaan kelas antara Pribumi dan Eropa.
Namun berbeda dengan roman asmara biasa, kisah cinta Minke-Annelies ini bagi saya hanya berupa utas. Substansi paling kuat justru ada pada konteks dan side story yang mengitarinya. Selain soal pembagian kelas, novel ini juga mengangkat isu soal posisi wanita dalam kultur Jawa, dan isu soal perbedaan Bangsa Belanda sendiri memandang politik kolonial. Pramoedya seolah mau menunjukkan berbagai ironi yang menuntut kita untuk bersikap: mau menyerah pada keadaan atau bangkit melawan. Dan ujung dari perlawanan tidak barang melulu soal menang, tapi juga soal menjaga kehormatan.
Yang saya sukai dari novel ini adalah latar kesejarahannya yang kaya. Membacanya mengajak saya mencicipi bagaimana rasanya hidup di Indonesia akhir abad ke-19. Dan itu membuat saya lebih respect pada perjuangan para pendahulu di era-era awal pergerakan. Meskipun tidak disinggung, saya jadi bisa memahami betapa revolusionernya gerakan pendidikan Muhammadiyah yang muncul belasan tahun berkelang.
Hal lain yang saya suka adalah banyaknya wisdom atau kata-kata mutiara yang muncul dalam novel ini. “Seorang terpelajar haruslah adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan”, ini mungkin salah satu yang cukup masyhur kita dengar. Kutipan ini asalnya adalah nasehat Jean Marais, seorang tukang Meubel, kepada Minke. Lalu ada pula kutipan, “Hidup dapat memberikan segala pada barang siapa tahu dan pandai menerima”, yang disampaikan ketika Nyai Ontosoroh ditanyai mengapa dirinya bisa terpelajar padahal hanya gundik. Dan salah satu kutipan yang jadi favorit saya, “Asal kau mengerti, Gus, semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang lain. Harus semakin mengenal batas. Kan itu tidak terlalu sulit difahami? Kalau orang tak tahu batas, Tuhan akan memaksanya tahu dengan cara-Nya sendiri.” Kutipan ini adalah nasehat Sang Ibu sebelum Minke menikah. Tentu masih banyak kutipan lainnya yang inspiratif dan menarik, yang bisa teman-teman baca sendiri. Saya yakin versi film pun tidak akan bisa mengcover semuanya.
Saya juga suka bagaimana sosok-sosok tangguh dalam novel ini ditampilkan tetap punya titik lemah. Tokoh Annelies misalnya, yang di satu sisi disebut-sebut punya kecantikan yang membuat para dewi iri, di sisi lain rupanya punya kerentanan psikis karena dirinya yang terbiasa kesepian. Lalu sosok Nyai Ontosoroh yang dicitrakan berpendirian, kaya raya, dan tak mudah menyerah, di baliknya ia berstatus gundik yang posisinya lemah secara hukum. Dan tokoh Minke sendiri, meskipun dia cerdas, dari keluarga terpandang, mandiri dan mapan secara ekonomi, ternyata di sisi lain punya sikap paranoid dan cacat moral. Tidak ada sosok sempurna, dan memang seperti itu kenyataan dunia. Kita lah yang perlu memandangnya secara proporsional.
Adapun yang tidak terlalu saya suka, ada pada sebagian skenario yang agaknya terlalu khayali. Meskipun konon novel ini diangkat dari tokoh nyata, nuansa fiksinya masih agak kentara. Contohnya tidak saya jabarkan di sini karena khawatir jadi spoiler. Tapi entahlah, bisa jadi juga itu semua hanya karena perbedaan zaman, sehingga respon yang saya anggap proper di masa sekarang barangkali bukan hal yang lazim di masa lalu.
Akhir kata, saya setuju dengan pendapat banyak orang bahwa ini novel yang cukup istimewa. Latar sejarahnya memberi wawasan baru, wisdom di dalamnya memberikan inspirasi, penuturannya khas kesusastraan lawas Indonesia, dan itu baik. Terakhir, alur ceritanya berhasil membawa pembaca mengikuti sebuah journey. Journey yang membuat saya berminat melanjutkan ke buku kedua dari tetralogi Buru: Anak Segala Bangsa.
----
Bagi teman-teman yang sudah pernah baca atau nonton filmnya yang mau menambahkan, atau menawarkan perspektif beda silakan disampaikan di kolom komentar ya.
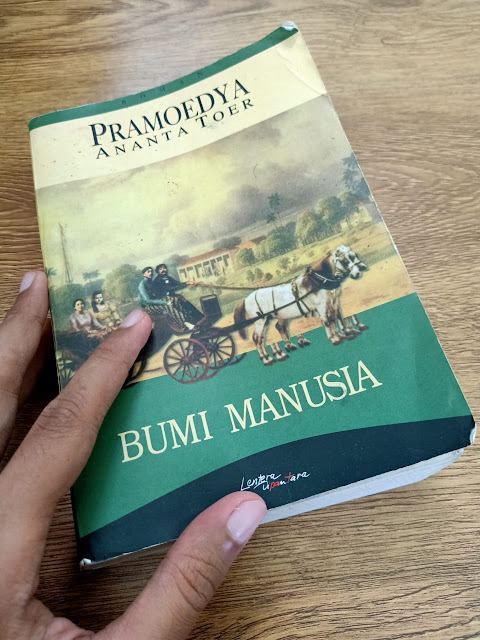
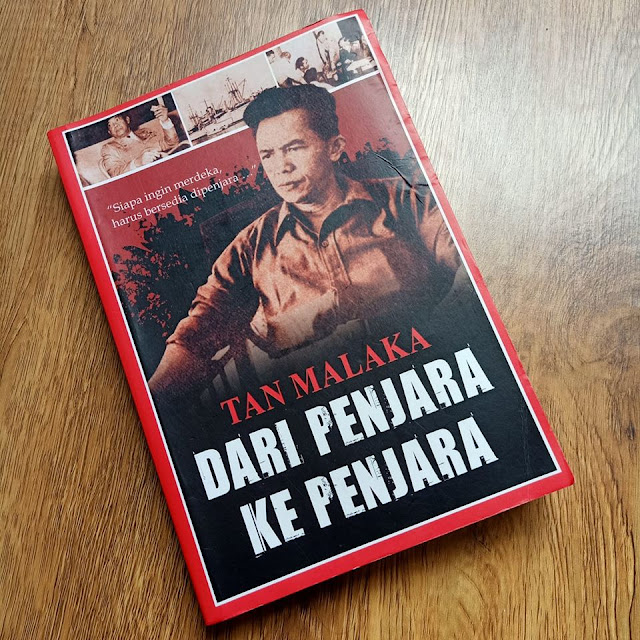
Comments
Post a Comment