Hidup Lebih Dari Sekedar Menang Atau Kalah [Resensi]
Judul: The Infinite Game
Penulis: Simon Sinek
Penerbit: Penguin Random House (2019)
Tebal: 251 hal
Genre: Kepemimpinan, pengembangan diri
To the point, buku ini pada intinya bercerita tentang sebuah konsep,
bahwa di dunia ini ada dua jenis permainan. Pertama adalah finite game, kedua
adalah infinite game. Finite game adalah permainan yang aturannya jelas, para pemainnya
jelas, cara mainnya jelas, batas waktunya jelas, serta ada tujuan atau obyektif
yang disepakati. Contohnya seperti pertandingan olah raga, sepakbola,
badminton, catur, lomba 17-an, dsb. Sebaliknya infinite game adalah permainan
yang aturannya tidak ajeg, dan pemainnya bebas keluar masuk, cara mainnya bisa
berubah-ubah, serta tidak ada limit waktu pula. Obyektif atau tujuannya juga tidak
seragam. Oleh karena itu orientasi dari dua jenis permainan ini pun berbeda.
Finite game bertujuan untuk menang, sedangkan infinite game bertujuan untuk
bertahan, survive, eksis selama-lama mungkin dalam permainan.
Menurut penulis, banyak aspek dalam kehidupan yang sesungguhnya merupakan infinite game, mulai dari bisnis, karir professional, politik, dan sebagainya, bahkan sampai kehidupan personal. Lalu, karena orientasi infinite game ini berbeda dengan finite game, maka mindset dalam menjalaninya pun tidak boleh dicampur. Kalau kita menggunakan mindset yang finite di game yang sebenernya infinite, maka yang terjadi adalah error, tidak sinkron, dan ujungnya bisa mengakibatkan kegagalan. Ini tidak heran mengingat mindset yang finite itu umumnya short termist. Jangka pendek. Sementara infinite game itu long term. Nah, berfokus pada hal yang short term berisiko mengabaikan hal-hal yang penting untuk long term.
Sebagai contoh penulis menceritakan bagaimana Microsoft di bawah Steve Balmer menjadi perusahaan yang mindsetnya serba finite. Di kalangan eksekutifnya, yang dipikirkan adalah bagaimana agar bisa selalu menang dari Apple. Tak lama setelah Apple meluncurkan iPod, Microsoft meluncurkan Zune untuk bersaing. Sementara di sisi lain Apple punya fokus berbeda. Eksekutif Apple tidak terlalu ambil pusing dengan Microsoft maupun Zune yang secara fitur lebih baik. Mereka lebih berpiki how to outdo themselves, bagaimana agar dapat menghasilkan produk yang lebih memenuhi demand customer, bukan hanya di saat ini, tapi juga di masa depan. Maka tidak lama setelah iPod keluar, lahirlah iPhone yang membuat Zune-nya Microsoft tadi sekaligus iPod punya mereka sendiri jadi usang dan ketinggalan zaman.
Di sini sekilas bisa kita amati perbedaan mindset dari kedua perusahaan tadi. Kalau mau kita dalami, banyak peristiwa antara Apple dan Microsoft ini yang menunjukkan gejala atau kecenderungan yang serupa. Apple tidak ragu meng-obsolete-kan produk mereka sendiri, karena memang orientasinya adalah masa depan: bagaimana produk mereka bisa terus terupgrade. Maka tidak heran Apple bisa menghasilkan produk yang jadi pendobrak. Sementara Microsoft, karena berfokus pada persaingan, mereka hanya sekedar menjadi bayang-bayang pihak lain. Karena itu pula, mereka kehilangan etos untuk menjadi pioneer sebagaimana di era Bill Gates.
Cerita Microsoft tadi adalah salah satu contoh bagaimana mindset yang finite itu bisa merusak kultur organisasi, karena menyebabkan kita salah persepsi atas prioritas. Yang harusnya didahulukan malah dikesampingkan. Mindset yang finite membuat kita jadi terpaku ke parameter-parameter yang ada di hadapan mata saja, sehingga lupa untuk mengeksplor berbagai kemungkinan lain yang saat itu mungkin belum kelihatan.
Lalu dampak lain dari mindset finite juga adalah rasa enggan untuk berubah . Salah satu contoh yang memberi gambaran tentang hal ini adalah cerita tentang Kodak. Jadi di masa-masa awal, di zaman George Eastman (sang pendiri), Kodak sebenernya termasuk perusahaan yang jadi pendobrak karena digerakkan oleh etos inovasi. Mereka bisa menghasilkan produk yang revolusioner di masanya, mulai dari film, cartridge film, slide proyektor, dan sebagainya yang bisa mengubah dunia fotografi yang sebelumnya ribet menjadi jauh lebih mudah. Mereka bahkan punya banyak hak paten karena invensi-invensi yang mereka lakukan.
Kejatuhan Kodak diawali dari orientasi para eksekutif sepeninggal Eastman yang mulai kehilangan etos inovasi tadi karena mereka merasa mempertahankan dominasi itu adalah hal paling penting. Ketika shifting tren ke arah digital udah mulai terlihat, dan mereka berhasil menciptakan paten di bidang fotografi digital, mereka tidak mau menggarap itu. Karena kalau mereka menggarap pasti model bisnis fotografi konvensional mereka akan jadi obsolete, dan tentunya membuat mereka menjadi kehilangan dominasi. Tapi market memang tidak bisa dibendung. Ketika Nikon dan Fuji mulai menggarap tren digital ini, Kodak mulai kehilangan pamor. Puncaknya ketika hak paten mereka habis di tahun 2007, Kodak pun nyaris bangkrut andai tidak mendapat proteksi dari Pemerintah AS.
Oleh karena itu dalam infinite game kita tidak mencari menang. Ada banyak sekali faktor atau parameter. Kadang untuk parameter tertentu kita bisa unggul, tapi untuk parameter lain bisa jadi pihak lain yang unggul. Toh kita tidak harus punya persepsi yang sama soal parameter mana yang layak dianggap lebih penting. Selain itu, kalaupun kita sepakat soal parameter tadi dan harus ada pihak yang menang, maka kemenangan itu pun sifatnya hanya sementara. Finite. Roda kehidupan berputar. Menjadi no.1 di suatu waktu, tidak menjamin kita mampu bertahan dalam jangka panjang. Malah sebaliknya, fokus untuk selalu menjadi no.1 justru beresiko kita mengabaikan hal-hal krusial yang menunjang eksistensi dalam jangka panjang.
Maka mindset yang tepat di infinite game itu adalah mindset yang berorientasi untuk survive, eksis, atau bertahan selama mungkin dalam permainan. Lalu agar bisa bertahan, kita butuh yang namanya just cause. Just cause ini adalah semacam tujuan besar yang menjadi motif atau alasan mengapa kita, organisasi kita, atau bisnis kita, itu eksis sejak awal. Jadi dalam infinit game, just cause inilah yang dikejar.
Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu just cause bisa berfungsii dengan baik. Akan tetapi dari semua itu kriteria yang paling penting barangkali just cause ini haruslah idealistic, dan resilient. Idealistik artinya ia muncul dari keresahan dan sifatnya agak utopis: bisa didekati tapi nyaris mustahil untuk dicapai. Adapun resilient artinya adalah tahan terhadap perubahan. Jadi meskipun situasi politik, budaya, maupun teknologi berubah, just cause ini tidak ikut berubah. Itu kenapa just cause ini umumnya tidak bicara tentang cara atau produk melainkan impact atau hasil.
Suatu organisasi atau entitas yang punya just cause akan cenderung lebih baik dalam menempatkan skala prioritas, sehingga sesuatu yang menunjang eksistensi jangka panjang pasti akan lebih didahulukan. Mereka tidak akan mengorbankan orang, integritas, atau kultur kerja hanya demi sekedar profit, bonus, atau sekedar jadi no.1.
Buku ini menurut saya cukup recommended untuk dibaca. Ada banyak penjelasan yang cukup membuka wawasan, misalnya bagaimana caranya menyusun suatu just cause supaya dia bisa serving kita di infinite game dengan baik. Ada juga penjelasan tentang beraneka konsep yang menarik, seperti konsep ethical fading, existensial flexibility, worthy rival, dan sebagainya, disamping berbagai ilustrasi dan kisah-kisah yang bagi saya cukup inspiratif.
Akhir kata, menjalani hidup dengan mindset yang infinite setidaknya memberikan kita beberapa manfaat. Pertama, ia bisa lebih menjamin eksistensi kita dalam jangka panjang, karena kita paham betul apa yang menjadi ultimate goal sehingga kita pun lebih aware dengan hal-hal yang lebih prioritas. Kedua, kita juga akan lebih terhindar dari perasaan insecure, karena kita memandang hidup jadinya bukan soal menang-menangan. Ketiga, kita memandang rival tidak untuk dikalahkan melainkan untuk mengevaluasi apa yang masih kurang dari diri kita saat ini supaya bisa kita perbaiki.
Wallohua’lam.
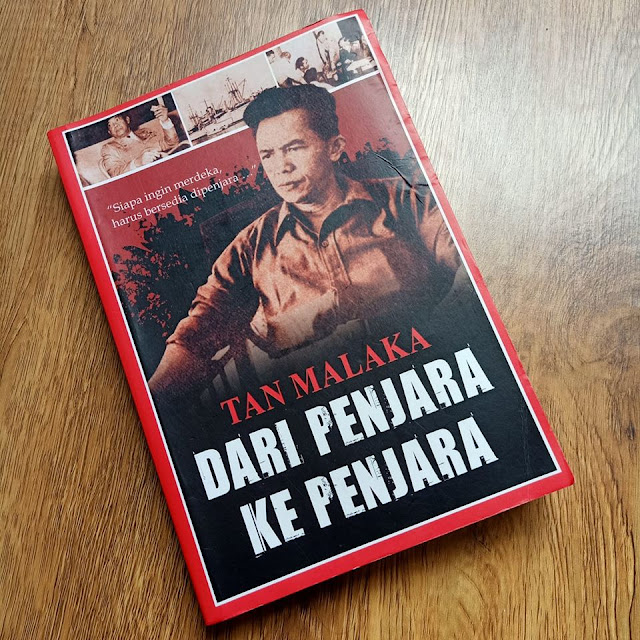
Comments
Post a Comment