9 Alasan Hadits Shahih Tapi Tidak Diamalkan
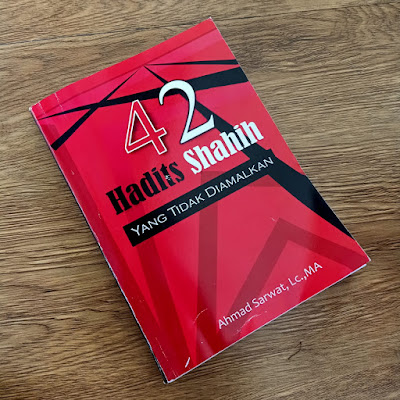
-------
Judul: 42 Hadits Shahih yang Tidak Diamalkan
Penulis: Ahmad Sarwat, Lc., MA
Penerbit: Rumah Fiqh Publishing (2019)
Kedudukan hadits sebagai tuntunan dan sumber hukum setelah Al Qur’an tentunya bukah hal asing lagi bagi sebagian besar kaum muslimin. Akan tetapi tidak sembarang hadits bisa diamalkan. Para ulama menetapkan syarat suatu hadits bisa diamalkan derajatnya haruslah shahih, atau minimal derajatnya hasan. Hadits shahih artinya hadits tersebut didukung oleh jalur periwayatan yang bersambung hingga ke sumber utama (yakni Nabi atau para Sahabat) dan setiap orang yang meriwayatkan hadits tersebut statusnya kredibel (memenuhi persyaratan). Selain itu hadits shahih haruslah terbebas dari syadz (keganjilan) dan illat (ketidakjelasan). Dengan demikian, hadits yang derajatnya shahih bisa diyakini benar-benar merupakan sabda Nabi (atau petuah sahabat Nabi), sehingga layak untuk diikuti.
Meskipun demikian ternyata ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu hadits shahih bisa tidak diamalkan. Dari buku ini, dijelaskan setidaknya ada 9 alasan.
1. Mansukh
Secara sederhana mansukh artinya telah terhapus hukumnya. Dengan kata lain suatu hadits benar-benar pernah disampaikan oleh Nabi akan tetapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi karena terdapat hadits baru yang menghapuskannya. Contoh dari hadits shahih semacam ini adalah larangan Nabi untuk melakukan ziarah kubur.
Di era-era awal turunnya wahyu, Nabi pernah melarang ummatnya untuk ziarah kubur akan tetapi di kemudian hari Nabi justru menganjurkan ummatnya ziarah kubur untuk mengingat mati. Dengan demikian larangan di awal sudah tidak berlaku. Para ulama mengatakan bahwa hikmah dari pelarangan di masa-masa awal tersebut adalah untuk menghindari praktik kesyirikan mengingat tradisi Islam belum mengakar kuat. Setelah konsep akidah mengkristal di masyarakat muslim, kekhawatiran perbuatan syirik di kuburan pun sirna sehingga Baginda Nabi memperbolehkan ziarah.
2. Tidak mengandung tasyri’
Hadits yang mengandung tasyri’ artinya hadits tersebut mengandung hukum, perintah/anjuran, atau larangan. Sebaliknya hadits yang tidak mengandung tasyri’ artinya tidak mengandung hal yang demikian. Satu hal yang perlu diingat, penulis buku ini menjelaskan bahwa justifikasi ada tidaknya tasyri’ dalam suatu hadits tetap merupakan domain para ulama fiqh.
Dalam buku ini dicontohkan diantaranya hadist yang menceritakan bahwa Nabi menggunakan tongkat ketika khutbah Jum’at serta hadits tentang anjuran bersiwak. Bagi sebagian kalangan, penggunaan tongkat merupakan bagian dari ritual khutbah sehingga pada beberapa masjid panitia biasa menyediakannya untuk khotib. Akan tetapi sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa tasyri’ hanya terdapat pada aspek khutbahnya saja sementara tongkatnya sendiri bukan merupakan tasyri’. Sehingga menurut kalangan kedua ini diperbolehkan berkhutbah tanpa tongkat. Hal yang sama juga terjadi pada hadits tentang anjuran bersiwak. Sebagian kalangan menganggap kayu siwak adalah sunnah yang perlu dipelihara, akan tetapi kalangan yang lain beranggapan tasyri’ hanya sekedar pada aspek bersiwaknya saja sementara alatnya yang berupa kayu siwak tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian menurut kalangan kedua ini boleh bersiwak dengan media selain kayu siwak.
3. Terikat konteks di mana konteks tersebut tidak ditemui pada si pengamal
Alasan ketiga suatu hadits shahih tidak diamalkan adalah karena sifat hadits tersebut yang sangat kontekstual, atau terikat dengan situasi spesifik di masa Nabi hidup. Contoh hadits semacam ini antara lain hadits yang menganjurkan untuk sholat dengan menggunakkan sendal/sepatu. Di masa Nabi lantai masjid hanya berupa tanah. Oleh karena itu sesuatu hal yang wajar apabila Nabi menganjurkan sholat dengan menggunakan sandal/sepatu, yang kurang pas apabila diamalkan di kondisi masa sekarang di mana lantai masjid atau rumah umumnya sudah menggunakan ubin atau sejenisnya.
Selain itu ada pula contoh lain yakni hadits tentang kebolehan untuk mengklaim pemilikan tanah bagi orang yang membangun dinding dan mengelolanya. Jadi sesuai adat di masa Nabi, tanah yang kosong atau menganggur dapat pindah klaim pemilikannya ke orang yang memanfaatkannya. Hal seperti ini wajar karena di saat itu belum ada negara dan tidak ada sistem yang mengatur hak-hak teritorial. Berbeda dengan di masa kini di mana seseorang dapat menguasai lahan tertentu tanpa batas waktu dengan dasar pengakuan oleh Negara dalam bentuk sertifikat, sehingga hadits dimaksud tidak serta-merta bisa diamalkan.
4. Berbeda lingkup/cakupan
Sebab lainnya suatu hadits shahih bisa tidak diamalkan adalah karena hadits tersebut berbicara tentang suatu hal yang lingkupnya terbatas. Dengan demikian mengamalkan hadits di luar lingkup bahasannya bisa termasuk sikap yang tidak pada tempatnya. Contoh dari hadits semacam ini adalah riwayat ‘Aisyah yang mengatakan bahwa mereka yang baru suci dari haidh diperintah Nabi untuk mengqodho puasa Ramadhan namun tidak diperintah untuk mengqodo sholat. Sebagian kalangan lantas berkesimpulan hadits ini menjadi dasar tidak adanya qodho dalam sholat secara umum. Padahal hadits tersebut ada lingkupnya, yakni hanya pada kaum wanita yang baru suci dari haidh.
Contoh lainnya yang dijelakan dalam buku adalah hadits tentang larangan jual beli menggunaan dua harga. Hadits ini cukup populer bagi sebagian kalangan untuk menjadi dasar pengharaman jual beli kredit, karena pada umumnya harga kredit berbeda dengan harga tunai. Padahal menurut penulis, lingkup dari hadits ini adalah transaksi yang disebut bai’ul inah. Bai’ul inah secara sederhana bisa dimaknai sebagai saling jual dan saling beli antara dua pihak, atas barang yang sama, di waktu yang sama, namun yang satu membayar secara tunai dan yang lain membayar secara kredit. Sebagai contoh, si A membeli emas dari si B secara tunai, si A menjual kembali ke si B dengan cara dicicil dan mengambil margin. Skema semacam inilah yang diharamkan karena sesungguhnya merupakan pinjam-meminjam di mana keuntungan yang diraup A adalah riba. Adapun jual beli kredit secara umum berada di luar cakupan hadits ini.
5. Memiliki illat yang tersembunyi
Dalam konteks ini, illat bisa dimaknai sebagai alasan berlakunya suatu hukum. Oleh karena itu ketika illat tidak ada maka hukum bisa menjadi tidak berlaku. Namun demikian, illat itu kadangkala tidak langsung dinyatakan dalam suatu hadits melainkan tersembunyi dan baru diketahui dari hadits lainnya. Contoh populer dari hadits semacam ini adalah hadits tentang isbal atau larangan menjulurkaan pakaian melewati mata kaki.
Bagi sebagian kalangan keharaman isbal berlaku mutlak, akan tetapi sebagian kalangan yang lain beranggapan hadits ini memiliki illat yakni kesombongan. Meskipun pada banyak hadits yang berbicara tentang isbal perihal kesombongan ini memang tidak secara eksplisit dijumpai, namun ada beberap hadits lain yang mengiringi keharaman ini dengan perbuatan sombong. Selain itu juga pernah ada riwayat tentang persetujuan Nabi atas Sahabat yang isbal karena Nabi mengetahui isbalnya Sahabat tersebut bukan karena sombong. Argumen ini ditambah lagi dengan keterangan bahwa kebiasaan di masa itu menjulurkan pakaian memang merupakan ekspresi dari kebanggaran diri. Oleh karena itu kalangan dimaksud menganggap isbal diperbolehkan apabila tidak dimaksudkan untuk sombong.
6. Terdapat hadits shahih lain yang berkata sebaliknya
Alasan berikutnya mengapa suatu hadits shahih tidak diamalkan adalah karena adanya hadits shahih lain yang memuat informasi sebaliknya. Contoh dari hadits ini adalah hadits tentang tata cara sujud dari posisi I’tidal dalam sholat. Sebagian hadits mengatakan bahwa bagian tubuh yang diletakkan terlebih dahulu adalah tangan, akan tetapi hadits lainnya mengatakan lutut. Perbedaan ini membuat pengamalan atas salah satu hadits berarti meninggalkan hadits yang lainnya.
Hadits yang secara kasatmata tampak kontradiktif seperti ini tidak sedikit jumlahnya. Akan tetapi ini bukan berarti inkonsistensi. Para ulama fiqh memiliki mekanisme untuk menyikapi hadits semacam ini. Adakalanya kontradiksi itu sesungguhnya bukanlah kontradiksi, melainkan sekedar petunjuk bahwa terdapat berbagai cara dalam melakukan sesuatu.
7. Perbedaan gaya bahasa
Majas atau gaya bahasan menjadi salah satu poin krusial dalam memaknai suatu hadits. Kadangkala suatu hadits diekspresikan Nabi dengan metafora tertentu (konotatif), sehingga pengamalannya tidak dilakukan secara literal (denotatif). Ini tidak lepas dari budaya sastra yang sudah berkembang di kalangan bangsa Arab ketika Nabi masih hidup. Contoh dari hadits semacam ini adalah hadits tentang pengandaian Nabi yang ingin membakar rumah para lelaki muslim yang tidak sholat berjamaah di masjid.
Sebagian kalangan menjadikan hadits tersebut sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki dewasa yang tidak memiliki udzur. Ada pula kalangan lainnya yang beranggapan bahwa hukumnya tidak sampai fardhu ‘ain, melainkan hanya fardhu kifayah, atau bahkan sekedar sunnah utama. Meski demikian para ulama sepakat bahwa membakar rumah bukan termasuk hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, karena hal tersebut tidak pernah benar-benar dilakukan Nabi. Diksi membakar rumah dalam hadits hanya merupakan metafora untuk menggambarkan betapa besarnya keutamaan yang ditinggalkan apabila meninggalkan sholat berjamaah.
8. Gestur Nabi belaka
Adapula hadits yang menunjukkan respon Nabi atas suatu hal dengan bahasa tubuh tertentu. Bahasa tubuh di sini terikat dengan kebiasaan dan pemaknaan di zaman itu yang bisa jadi tidak selalu sinkron dengan semua tempat dan kondisi. Oleh karena itu pengamalannya tidak bisa serta merta, melainkan perlu dengan tetap memperhatika faktor-faktor kebiasaan dan kewajaran setempat.
Contoh dari hadits semacam ini adalah hadits yang menceritakan “pukulan” Nabi ke dada Muadz bin Jabal sebagai respon beliau atas sikapnya yang akan menggunakan ijtihad apabila suatu hal tidak dijumpai petunjuknya dalam Qur’an mupun sunnah. Di sini, pukulan di dada itu merupakan bentuk ekspresi persetujuan, bukan penolakan apalagi untuk menyakiti. Oleh karena itu di kitab-kitab terjemahan hadits ini meskipun menggunakan redaksi “dhoroba” yang berarti pukulan dalam bahasa arab akan tetapi sering diterjemahkan dengan tepukan.
9. Kekhususan bagi Nabi semata
Alasan terakhir yang dijelaskan di dalam buku sebagai penyebab suatu hadits shahih tidak diamalkan adalah karena suatu hal itu hanya berlaku pada diri Nabi dan tidak berlaku bagi ummatnya. Nabi adalah manusia pilihan dan oleh karenaya amat wajar apabila beliau Alloh anggap memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain.
Contoh dari hadits semacam ini adalah tentang Nabi yang menikahi lebih dari empat orang istri dalam suatu waktu. Kaum muslimin tidak bisa menjadikan hadits ini sebagai dalil pembolehan untuk beristri lebih dari empat orang, karena hal ini sekedar bentuk kekhususan pada Nabi. Kekhususan ini nyata karena Nabi juga mendapat hukum khusus pula yakni beliau dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah, Nabi diwajibkan qiyamullail setiap malam, dan isteri-isteri beliau tidak boleh lagi dinikahi setelah Nabi wafat. Hukum khusus ini tidak diberikan kepada umat beliau.
-------
Pada prinsipnya jargon kembali ke Al Qur’an dan sunnah tetap merupakan panduan secara umum. Seorang muslim harus mendasarkan seluruh perilakunya kepada kepada ketentuan yang berasal dua sumber tersebut. Apa yang diperintahkan dikerjakan, dan apa yang dilarang ditinggalkan. Akan tetapi secara khusus, seseorang tidak bisa dengan serta-merta mengamalkan sesuatu, dalam hal ini hadist shahih, hanya karena hal tersebut tertulis di dalamnya. Dibutuhkan penjelasan dari ulama yang kompeten agar pemahamannya tepat dan tidak salah kaprah.
Tentu adanya perbedaan pendapat ulama dalam menilai hadits adalah sebuah keniscayaan. Adakalanya seorang ulama lebih cenderung menguatkan suatu pendapat ketimbang pendapat yang lain. Namun itu tidak masalah. Bagi kalangan awam, mendasari perbuatan pada pendapat seorang ulama masih lebih baik daripada mencoba-coba mencari pemahaman sendiri tanpa ilmu.
Wallohua’lam
Judul: 42 Hadits Shahih yang Tidak Diamalkan
Penulis: Ahmad Sarwat, Lc., MA
Penerbit: Rumah Fiqh Publishing (2019)
Kedudukan hadits sebagai tuntunan dan sumber hukum setelah Al Qur’an tentunya bukah hal asing lagi bagi sebagian besar kaum muslimin. Akan tetapi tidak sembarang hadits bisa diamalkan. Para ulama menetapkan syarat suatu hadits bisa diamalkan derajatnya haruslah shahih, atau minimal derajatnya hasan. Hadits shahih artinya hadits tersebut didukung oleh jalur periwayatan yang bersambung hingga ke sumber utama (yakni Nabi atau para Sahabat) dan setiap orang yang meriwayatkan hadits tersebut statusnya kredibel (memenuhi persyaratan). Selain itu hadits shahih haruslah terbebas dari syadz (keganjilan) dan illat (ketidakjelasan). Dengan demikian, hadits yang derajatnya shahih bisa diyakini benar-benar merupakan sabda Nabi (atau petuah sahabat Nabi), sehingga layak untuk diikuti.
Meskipun demikian ternyata ada beberapa alasan yang menyebabkan suatu hadits shahih bisa tidak diamalkan. Dari buku ini, dijelaskan setidaknya ada 9 alasan.
1. Mansukh
Secara sederhana mansukh artinya telah terhapus hukumnya. Dengan kata lain suatu hadits benar-benar pernah disampaikan oleh Nabi akan tetapi hukumnya sudah tidak berlaku lagi karena terdapat hadits baru yang menghapuskannya. Contoh dari hadits shahih semacam ini adalah larangan Nabi untuk melakukan ziarah kubur.
Di era-era awal turunnya wahyu, Nabi pernah melarang ummatnya untuk ziarah kubur akan tetapi di kemudian hari Nabi justru menganjurkan ummatnya ziarah kubur untuk mengingat mati. Dengan demikian larangan di awal sudah tidak berlaku. Para ulama mengatakan bahwa hikmah dari pelarangan di masa-masa awal tersebut adalah untuk menghindari praktik kesyirikan mengingat tradisi Islam belum mengakar kuat. Setelah konsep akidah mengkristal di masyarakat muslim, kekhawatiran perbuatan syirik di kuburan pun sirna sehingga Baginda Nabi memperbolehkan ziarah.
2. Tidak mengandung tasyri’
Hadits yang mengandung tasyri’ artinya hadits tersebut mengandung hukum, perintah/anjuran, atau larangan. Sebaliknya hadits yang tidak mengandung tasyri’ artinya tidak mengandung hal yang demikian. Satu hal yang perlu diingat, penulis buku ini menjelaskan bahwa justifikasi ada tidaknya tasyri’ dalam suatu hadits tetap merupakan domain para ulama fiqh.
Dalam buku ini dicontohkan diantaranya hadist yang menceritakan bahwa Nabi menggunakan tongkat ketika khutbah Jum’at serta hadits tentang anjuran bersiwak. Bagi sebagian kalangan, penggunaan tongkat merupakan bagian dari ritual khutbah sehingga pada beberapa masjid panitia biasa menyediakannya untuk khotib. Akan tetapi sebagian kalangan yang lain berpendapat bahwa tasyri’ hanya terdapat pada aspek khutbahnya saja sementara tongkatnya sendiri bukan merupakan tasyri’. Sehingga menurut kalangan kedua ini diperbolehkan berkhutbah tanpa tongkat. Hal yang sama juga terjadi pada hadits tentang anjuran bersiwak. Sebagian kalangan menganggap kayu siwak adalah sunnah yang perlu dipelihara, akan tetapi kalangan yang lain beranggapan tasyri’ hanya sekedar pada aspek bersiwaknya saja sementara alatnya yang berupa kayu siwak tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian menurut kalangan kedua ini boleh bersiwak dengan media selain kayu siwak.
3. Terikat konteks di mana konteks tersebut tidak ditemui pada si pengamal
Alasan ketiga suatu hadits shahih tidak diamalkan adalah karena sifat hadits tersebut yang sangat kontekstual, atau terikat dengan situasi spesifik di masa Nabi hidup. Contoh hadits semacam ini antara lain hadits yang menganjurkan untuk sholat dengan menggunakkan sendal/sepatu. Di masa Nabi lantai masjid hanya berupa tanah. Oleh karena itu sesuatu hal yang wajar apabila Nabi menganjurkan sholat dengan menggunakan sandal/sepatu, yang kurang pas apabila diamalkan di kondisi masa sekarang di mana lantai masjid atau rumah umumnya sudah menggunakan ubin atau sejenisnya.
Selain itu ada pula contoh lain yakni hadits tentang kebolehan untuk mengklaim pemilikan tanah bagi orang yang membangun dinding dan mengelolanya. Jadi sesuai adat di masa Nabi, tanah yang kosong atau menganggur dapat pindah klaim pemilikannya ke orang yang memanfaatkannya. Hal seperti ini wajar karena di saat itu belum ada negara dan tidak ada sistem yang mengatur hak-hak teritorial. Berbeda dengan di masa kini di mana seseorang dapat menguasai lahan tertentu tanpa batas waktu dengan dasar pengakuan oleh Negara dalam bentuk sertifikat, sehingga hadits dimaksud tidak serta-merta bisa diamalkan.
4. Berbeda lingkup/cakupan
Sebab lainnya suatu hadits shahih bisa tidak diamalkan adalah karena hadits tersebut berbicara tentang suatu hal yang lingkupnya terbatas. Dengan demikian mengamalkan hadits di luar lingkup bahasannya bisa termasuk sikap yang tidak pada tempatnya. Contoh dari hadits semacam ini adalah riwayat ‘Aisyah yang mengatakan bahwa mereka yang baru suci dari haidh diperintah Nabi untuk mengqodho puasa Ramadhan namun tidak diperintah untuk mengqodo sholat. Sebagian kalangan lantas berkesimpulan hadits ini menjadi dasar tidak adanya qodho dalam sholat secara umum. Padahal hadits tersebut ada lingkupnya, yakni hanya pada kaum wanita yang baru suci dari haidh.
Contoh lainnya yang dijelakan dalam buku adalah hadits tentang larangan jual beli menggunaan dua harga. Hadits ini cukup populer bagi sebagian kalangan untuk menjadi dasar pengharaman jual beli kredit, karena pada umumnya harga kredit berbeda dengan harga tunai. Padahal menurut penulis, lingkup dari hadits ini adalah transaksi yang disebut bai’ul inah. Bai’ul inah secara sederhana bisa dimaknai sebagai saling jual dan saling beli antara dua pihak, atas barang yang sama, di waktu yang sama, namun yang satu membayar secara tunai dan yang lain membayar secara kredit. Sebagai contoh, si A membeli emas dari si B secara tunai, si A menjual kembali ke si B dengan cara dicicil dan mengambil margin. Skema semacam inilah yang diharamkan karena sesungguhnya merupakan pinjam-meminjam di mana keuntungan yang diraup A adalah riba. Adapun jual beli kredit secara umum berada di luar cakupan hadits ini.
5. Memiliki illat yang tersembunyi
Dalam konteks ini, illat bisa dimaknai sebagai alasan berlakunya suatu hukum. Oleh karena itu ketika illat tidak ada maka hukum bisa menjadi tidak berlaku. Namun demikian, illat itu kadangkala tidak langsung dinyatakan dalam suatu hadits melainkan tersembunyi dan baru diketahui dari hadits lainnya. Contoh populer dari hadits semacam ini adalah hadits tentang isbal atau larangan menjulurkaan pakaian melewati mata kaki.
Bagi sebagian kalangan keharaman isbal berlaku mutlak, akan tetapi sebagian kalangan yang lain beranggapan hadits ini memiliki illat yakni kesombongan. Meskipun pada banyak hadits yang berbicara tentang isbal perihal kesombongan ini memang tidak secara eksplisit dijumpai, namun ada beberap hadits lain yang mengiringi keharaman ini dengan perbuatan sombong. Selain itu juga pernah ada riwayat tentang persetujuan Nabi atas Sahabat yang isbal karena Nabi mengetahui isbalnya Sahabat tersebut bukan karena sombong. Argumen ini ditambah lagi dengan keterangan bahwa kebiasaan di masa itu menjulurkan pakaian memang merupakan ekspresi dari kebanggaran diri. Oleh karena itu kalangan dimaksud menganggap isbal diperbolehkan apabila tidak dimaksudkan untuk sombong.
6. Terdapat hadits shahih lain yang berkata sebaliknya
Alasan berikutnya mengapa suatu hadits shahih tidak diamalkan adalah karena adanya hadits shahih lain yang memuat informasi sebaliknya. Contoh dari hadits ini adalah hadits tentang tata cara sujud dari posisi I’tidal dalam sholat. Sebagian hadits mengatakan bahwa bagian tubuh yang diletakkan terlebih dahulu adalah tangan, akan tetapi hadits lainnya mengatakan lutut. Perbedaan ini membuat pengamalan atas salah satu hadits berarti meninggalkan hadits yang lainnya.
Hadits yang secara kasatmata tampak kontradiktif seperti ini tidak sedikit jumlahnya. Akan tetapi ini bukan berarti inkonsistensi. Para ulama fiqh memiliki mekanisme untuk menyikapi hadits semacam ini. Adakalanya kontradiksi itu sesungguhnya bukanlah kontradiksi, melainkan sekedar petunjuk bahwa terdapat berbagai cara dalam melakukan sesuatu.
7. Perbedaan gaya bahasa
Majas atau gaya bahasan menjadi salah satu poin krusial dalam memaknai suatu hadits. Kadangkala suatu hadits diekspresikan Nabi dengan metafora tertentu (konotatif), sehingga pengamalannya tidak dilakukan secara literal (denotatif). Ini tidak lepas dari budaya sastra yang sudah berkembang di kalangan bangsa Arab ketika Nabi masih hidup. Contoh dari hadits semacam ini adalah hadits tentang pengandaian Nabi yang ingin membakar rumah para lelaki muslim yang tidak sholat berjamaah di masjid.
Sebagian kalangan menjadikan hadits tersebut sebagai dalil wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki dewasa yang tidak memiliki udzur. Ada pula kalangan lainnya yang beranggapan bahwa hukumnya tidak sampai fardhu ‘ain, melainkan hanya fardhu kifayah, atau bahkan sekedar sunnah utama. Meski demikian para ulama sepakat bahwa membakar rumah bukan termasuk hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, karena hal tersebut tidak pernah benar-benar dilakukan Nabi. Diksi membakar rumah dalam hadits hanya merupakan metafora untuk menggambarkan betapa besarnya keutamaan yang ditinggalkan apabila meninggalkan sholat berjamaah.
8. Gestur Nabi belaka
Adapula hadits yang menunjukkan respon Nabi atas suatu hal dengan bahasa tubuh tertentu. Bahasa tubuh di sini terikat dengan kebiasaan dan pemaknaan di zaman itu yang bisa jadi tidak selalu sinkron dengan semua tempat dan kondisi. Oleh karena itu pengamalannya tidak bisa serta merta, melainkan perlu dengan tetap memperhatika faktor-faktor kebiasaan dan kewajaran setempat.
Contoh dari hadits semacam ini adalah hadits yang menceritakan “pukulan” Nabi ke dada Muadz bin Jabal sebagai respon beliau atas sikapnya yang akan menggunakan ijtihad apabila suatu hal tidak dijumpai petunjuknya dalam Qur’an mupun sunnah. Di sini, pukulan di dada itu merupakan bentuk ekspresi persetujuan, bukan penolakan apalagi untuk menyakiti. Oleh karena itu di kitab-kitab terjemahan hadits ini meskipun menggunakan redaksi “dhoroba” yang berarti pukulan dalam bahasa arab akan tetapi sering diterjemahkan dengan tepukan.
9. Kekhususan bagi Nabi semata
Alasan terakhir yang dijelaskan di dalam buku sebagai penyebab suatu hadits shahih tidak diamalkan adalah karena suatu hal itu hanya berlaku pada diri Nabi dan tidak berlaku bagi ummatnya. Nabi adalah manusia pilihan dan oleh karenaya amat wajar apabila beliau Alloh anggap memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain.
Contoh dari hadits semacam ini adalah tentang Nabi yang menikahi lebih dari empat orang istri dalam suatu waktu. Kaum muslimin tidak bisa menjadikan hadits ini sebagai dalil pembolehan untuk beristri lebih dari empat orang, karena hal ini sekedar bentuk kekhususan pada Nabi. Kekhususan ini nyata karena Nabi juga mendapat hukum khusus pula yakni beliau dan keluarganya tidak boleh menerima sedekah, Nabi diwajibkan qiyamullail setiap malam, dan isteri-isteri beliau tidak boleh lagi dinikahi setelah Nabi wafat. Hukum khusus ini tidak diberikan kepada umat beliau.
-------
Pada prinsipnya jargon kembali ke Al Qur’an dan sunnah tetap merupakan panduan secara umum. Seorang muslim harus mendasarkan seluruh perilakunya kepada kepada ketentuan yang berasal dua sumber tersebut. Apa yang diperintahkan dikerjakan, dan apa yang dilarang ditinggalkan. Akan tetapi secara khusus, seseorang tidak bisa dengan serta-merta mengamalkan sesuatu, dalam hal ini hadist shahih, hanya karena hal tersebut tertulis di dalamnya. Dibutuhkan penjelasan dari ulama yang kompeten agar pemahamannya tepat dan tidak salah kaprah.
Tentu adanya perbedaan pendapat ulama dalam menilai hadits adalah sebuah keniscayaan. Adakalanya seorang ulama lebih cenderung menguatkan suatu pendapat ketimbang pendapat yang lain. Namun itu tidak masalah. Bagi kalangan awam, mendasari perbuatan pada pendapat seorang ulama masih lebih baik daripada mencoba-coba mencari pemahaman sendiri tanpa ilmu.
Wallohua’lam
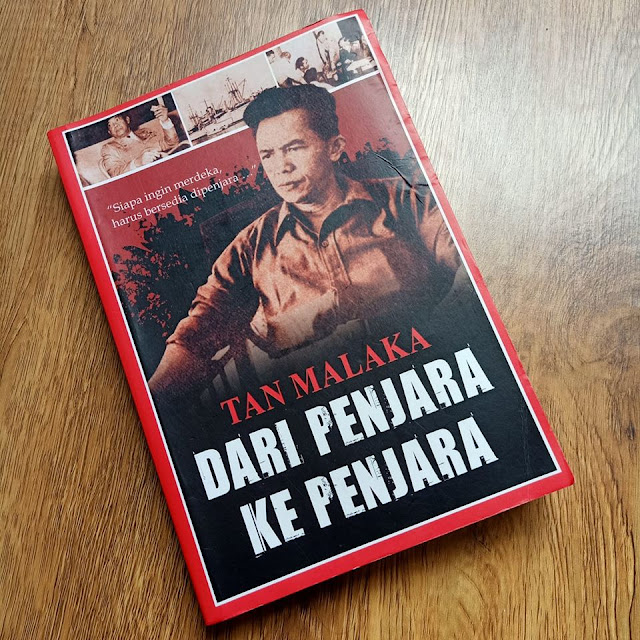
Comments
Post a Comment