Mensufikan Salafi dan Mensalafikan Sufi [Resensi]
Ini salah satu buku yang jadi temen di Ramadhan kemarin. Tulisan Yusuf Qardhawi. Cukup tipis, tebalnya hanya sekitar 217 halaman. Terbitan Penerbit Uswah Tahun 2008. Terjemahan dari yang judul aslinya “Taisir Fiqh as Suluk fi Dhau’ al Qur’an wa as Sunnah (al ‘Ilm wal Hayah ar Robbaniyyah)”.
Dari kata pengantarnya, pembaca
akan tahu buku ini merupakan respon penulis atas adanya eksistensi dua kelompok
yang sering dipersepsikan bertentangan satu sama lain, yakni sufi dan salafi. Yang
satu cenderung saklek pada aspek fikih sehingga terkesan mengabaikan aspek tasawuf,
sementara yang satu lagi menitikberatkan perhatiannya pada aspek tasawuf sehingga
terkesan mengabaikan aspek fikih.
Dengan buku ini, penulis hendak
menjelaskan bahwa sikap ideal adalah kembali kepada prinsip dasar Islam dalam
memandang fikih dan tasawuf, yakni dengan berkaca kepada kehidupan Robbani yang
dicontohkan Rosululloh saw. Demikian pula kehidupan para sahabat dan
pengikutnya. Dari mereka umat bisa melihat bahwa aspek tasawuf sangat lekat
dengan kehidupan keseharian dan pada saat yang bersamaan mereka juga sangat
konsisten dalam menjaga syariat Alloh. Dengan demikian fikih dan tasawuf sesungguhnya
merupakan dua aspek yang padu tidak perlu dipertentangkan.
Hal yang kurang baik adalah
ketika pembahasan fikih kering dari esensi dan penghayatan sehingga tidak mampu
menjangkau sisi rohani. Di sisi lain, adalah hal yang keliru pula apabila sisi
penghayatan ini menjadi begitu dominan sehingga syariat dan aspek-aspek formalistik
agama seolah tidak diperlukan.
Meskipun demikian, tendensi
kritik dalam buku ini memang terasa lebih ditujukan kepada kaum sufi. Itu
mengingat kadar kekeliruan di kelompok tersebut kadang memang cukup fatal. Ada
kalangan sufi yang lebih mengutamakan ilham (wangsit) atau pengalaman batin guru-gurunya
ketimbang syariat dalam agama. Sehingga apabila ilham tersebut mendorong kepada
suatu hal sementara syariat mendorong ke hal lain, maka yang didahulukan adalah
ilham tersebut, dengan berbagai argumentasinya.
Sikap semacam itu menurut penulis
adalah sikap yang keliru. Oleh Karena itu penulis mengambil porsi yang cukup
besar dari buku ini (hampir separuh isi buku) untuk membahas bab Ilmu. Pada
intinya penulis hendak menjelaskan bahwa ilmu punya kedudukan yang penting dalam
Islam. Ilmu mendahului amal. Ilmu adalah syarat agar ibadah bernas dan makbul. Ilmu
adalah perangkat yang diberikan pada para nabi dan rosul dan menjadi kelebihan
manusia atas malaikat. Ilmu lebih mampu mengangkat martabat manusia di hadapan
Alloh ketimbang ibadah mengangkatnya. Selain itu iman yang dihasilkan dari nalar
kritis karena ilmu akan lebih baik ketimbang iman yang berasal dari sekedar
taklid. Bagaimanapun perintah, larangan, dan adab syariah yang lahir dari ilmu adalah
bingkai tasawuf (kehidupan rohani) yang tidak boleh diterabas. Hal yang
sesungguhnya juga diterima oleh tokoh sufi yang hanif generasi awal seperti Abu Zaid, Al Junaid bin Muhammad,
atau Abu Sulaiman ad Darini.
Terakhir, demi obyektifitas penulis
juga mengajak pembacanya untuk tidak menafikan hal-hal yang menjadi jargon di
kalangan sufi seperti kasyaf (intuisi), ilham, dan karomah. Ketiganya merupakan
sesuatu yang eksis dan merupakan bagian dari karunia Alloh bagi siapa yang Dia
kehendaki. Akan tetapi penerimaan tersebut tetap dibatasi oleh kaidah agama
yang sudah diakui dan hukum syariat yang sudah disepakati. Sebagai contoh,
apabila seorang hakim yang sholih berdasarkan kasyafnya merasa seseorang itu
bersalah dalam sebuah perkara, ia tidak boleh memutuskan bersalah sampai
terdapat bukti nyata atas kesalahannya. Kendatipun intuisi tersebut bisa benar,
akan tetapi keputusan tanpa bukti adalah hal yang keliru berdasarkan kaidah
agama.
Tentu saja bahasan singkat dalam buku
tidak akan cukup untuk meng-convert seorang salafi menjadi sufi ataupun
sebaliknya seperti yang dimuat di judulnya. Akan tetapi bagi pembaca yang bukan
merupakan bagian dari kedua kelompok itu saya kira akan terbantu untuk
memandang dialektika sufi dan salafi ini secara lebih obyektif. Bahasannya akan
berfungsi menambah, atau sekurang-kurangnya menyegarkan kembali, wawasan
tentang hubungan ilmu-amal-syariat. Akhir kata, tak masalah mau menjadi salafi
atau sufi. Yang penting adalah ittiba’ pada Rosululloh saw dalam berislam, lair
dan batin.
Wallohua’lam.

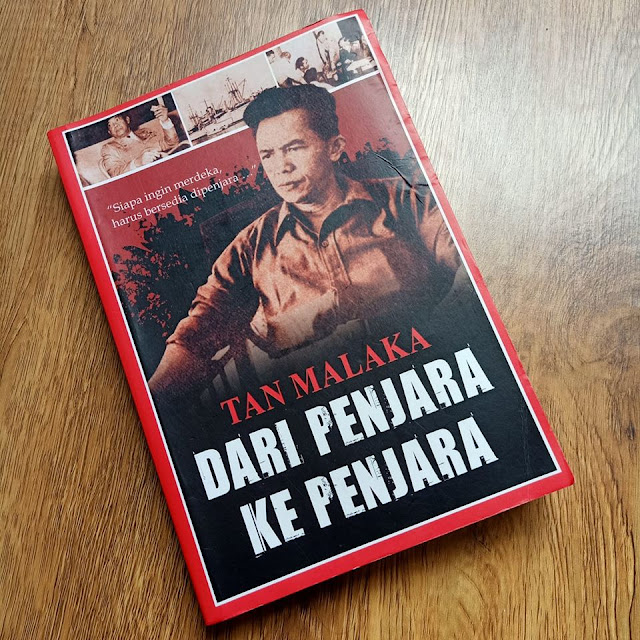
Comments
Post a Comment