Standar Tsubasa
 Saya teringat sebuah fragmen di kartun sepakbola Captain Tsubasa. Ketika itu, Tsubasa telah menandatangani kontrak bermain di klub tenar Spanyol, Catalunya. Sang manajer tim memang sudah lama memperhatikan konsistensi permainan yang baik dari orang Jepang tersebut. Selain memiliki akurasi dribel, umpan, dan tembakan yang tinggi, Tsubasa juga dinilainya mampu bermain di segala posisi. Peran sebagai bek, penyerang, sayap, dan gelandang mampu dijalani Tsubasa dengan sangat baik. Tapi justru karena kemampuan multifungsi itulah sang manajer bingung menempatkan Tsubasa di posisi apa di tim inti. Sang manajer pun akhirnya memanggil Tsubasa dan menanyakan posisi apa yang diinginkannya di tim inti. Dari sebelas posisi, hanya dua posisi yang tidak bisa dipilih Tsubasa, yakni kiper dan gelandang serang. Kiper tentu tidak bisa dipilih karena Tsubasa memang dikenal tidak pernah menjadi kiper, dan gelandang serang juga tidak bisa dipilih karena di posisi itu sudah bercokol pemain Catalunya yang juga pemain terbaik di Eropa saat itu. Apa jawaban Tsubasa? Tsubasa tidak mengacuhkan pilihan yang disediakan. Yang ia pilih adalah posisi gelandang serang! Jawaban yang berati menantang duel skill sang pemain terbaik Eropa.
Saya teringat sebuah fragmen di kartun sepakbola Captain Tsubasa. Ketika itu, Tsubasa telah menandatangani kontrak bermain di klub tenar Spanyol, Catalunya. Sang manajer tim memang sudah lama memperhatikan konsistensi permainan yang baik dari orang Jepang tersebut. Selain memiliki akurasi dribel, umpan, dan tembakan yang tinggi, Tsubasa juga dinilainya mampu bermain di segala posisi. Peran sebagai bek, penyerang, sayap, dan gelandang mampu dijalani Tsubasa dengan sangat baik. Tapi justru karena kemampuan multifungsi itulah sang manajer bingung menempatkan Tsubasa di posisi apa di tim inti. Sang manajer pun akhirnya memanggil Tsubasa dan menanyakan posisi apa yang diinginkannya di tim inti. Dari sebelas posisi, hanya dua posisi yang tidak bisa dipilih Tsubasa, yakni kiper dan gelandang serang. Kiper tentu tidak bisa dipilih karena Tsubasa memang dikenal tidak pernah menjadi kiper, dan gelandang serang juga tidak bisa dipilih karena di posisi itu sudah bercokol pemain Catalunya yang juga pemain terbaik di Eropa saat itu. Apa jawaban Tsubasa? Tsubasa tidak mengacuhkan pilihan yang disediakan. Yang ia pilih adalah posisi gelandang serang! Jawaban yang berati menantang duel skill sang pemain terbaik Eropa.Kisah di atas memang fiksi, tapi relevansinya banyak kita temukan di kehidupan nyata. Kisah serupa sangat mungkin ada di dunia sepakbola sebenarnya. Ini cerita tentang standar hidup. Tentang ekspektasi terhadap diri sendiri. Bagi Tsubasa, bermain di klub besar Eropa (tentunya di tim inti) adalah salah satu impiannya. Tsubasa pada saat itu bisa memilih untuk menempati posisi yang lain lalu dengan itu dia pasti diterima di tim inti. Namun ketika impiannya itu nyaris di depan mata, ia tidak bergeming sejengkalpun untuk menurunkan standarnya. Ia memilih mencoba memaksimalkan potensinya, memenuhi ekspektasi dirinya untuk menjadi gelandang serang kendati harus bersaing dengan pemain utama yang lebih berpengalaman.
Saya pun teringat sebuah komentar di rubrik Kompasiana. Intinya, sang komentator mengatakan bahwa orang-orang Indonesia didominasi oleh orang-orang yang punya standar rendah. Dalam apapun. Ya pendidikan, ya kesehatan, ya kesejahteraan, ya pelayanan publik, bahkan hingga sampai standar aktualisasi diri. Secara pribadi saya kurang setuju dengan generalisasi ‘orang-orang Indonesia’ yang disampaiikan komentator tersebut, tapi secara esensi, maksud beliau saya kira ada benarnya. Kita tidak sedang berbicara tentang standar yang diberikan orang pada kita, tapi standar yang kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Bisa jadi banyak di antara kita yang tergesa-gesa merasa cukup dengan pencapaian diri saat ini dan tak terpacu untuk jadi jauh lebih baik lagi. Kita mungkin merasa cukup beribadah hanya dengan sholat 5 waktu dan puasa wajib Ramadhan saja padahal ada ibadah nawafil (sunnah) yang bisa kita lakukan. Kita barangkali merasa cukup dengan hafal juz 30 saja padahal kita bisa terus berusaha mencoba menghafal 29 juz yang lainnya. Kita pun kadang merasa cukup dengan sedekah 1000 rupiah saja setiap Jum’at tanpa berazzam suatu saat nanti bersedekah 100.000 rupiah setiap pekan. Kita bisa jadi merasa cukup dengan ilmu agama yang dipelajari di SD, SMP, dan SMA saja padahal kita bisa mengikuti majlis ilmu yang bertebaran di mana-mana. Kita mungkin merasa cukup hanya dengan sejahtera sendiri tanpa berkeinginan ikut menyejahterakan orang-orang di sekeliling kita. Kita barangkali merasa telah cukup berkontribusi untuk negeri dengan menjadi sosok yang mandiri dan tak membebani negara padahal kita bisa turut memberdayaan masyarakat sesuai versi kita. Kita mungkin merasa cukup berdakwah sendiri padahal ada organisasi dakwah yang gerakannya bisa memberikan percepatan terhadap perbaikan bangsa. Dan sederet contoh lainnya yang bisa pembaca amati sendiri.
Anthony Robbins dalam bukunya ‘Awakens the Giant Within’ menyatakan bahwa satu cara yang perlu ditempuh untuk membangunkan raksasa (potensi) yang kita miliki adalah dengan menaikkan standar diri kita (raise your standard). Saat kita menaikkan standar diri kita, secara otomatis muncul tuntutan untuk memberi dan melakukan sesuatu yang lebih. Konsekuensinya logis, jika kita konsisten meningkatkan standar diri, maka waktu kita untuk berleha-leha akan berkurang, energi lebih banyak terkuras, uang lebih banyak terpakai, sumberdaya diri kita yang lain lebih mudah tersita. Namun seperti kisah Pursuit of Happiness, itulah cara kita untuk mengejar kebahagiaan. Dengan memberi dan do something bigger-lah kita mengaktualisasikan rasa syukur kita. Betapa tidak? Apakah arti syukur hanya mengucap berterima kasih? Tidak. Dimensi syukur yang lain adalah menggunakan nikmat Alloh itu sesuai keinginan Alloh. Jadi, jika Alloh mengaruniai kita potensi 100%, maka wujud syukur adalah memanfaatkan 100% potensi itu di jalan Alloh. Jika kita hanya memanfaatkan 80% potensi, itu artinya ada 20% karunia yang belum benar-benar kita syukuri. Cukup make sense bukan?
Seperti Tsubasa yang memilih untuk mencapai target terbaiknya, kita pun mesti demikian jika hendak menjadi sosok istimewa di mata manusia, terlebih lagi di hadapan Alloh. Sadarilah kawan, ada ruang-ruang standar diri kita yang masih kosong dan perlu kita isi. Standar diri kita, adalah kualitas kita, dan kualitas bangsa kita. Seperti kata Ibu Marwah Daud Ibrahim, jika kesuksesan suatu bangsa adalah akumulasi dari kesuksesan individu-individunya, maka optimalisasi potensi bangsa juga tumbuh dari optimalisasi potensi warganya. Betul tidak?
Oh ya, pembaca tahu bagaimana kelanjutan cerita Tsubasa di atas? Tsubasa akhirnya diminta bermain di tim kelas dua (bukan di tim utama), hanya untuk membuktikan dirinya punya kelas yang sama dengan pemain-pemain terbaik Eropa. Kurang dari 3 bulan, Tsubasa akhirnya di sandingkan dengan sang bintang, di posisi gelandang serang!
Let’s raise our standard
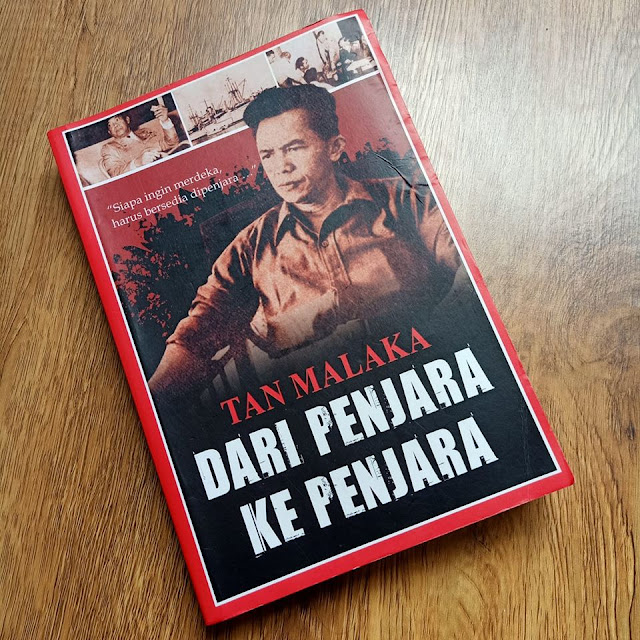
kak ternyata penikmat tsubasa juga ya, selain ternyata baru sekarang tersadar dengan pesan moral yan terselip didalamnya. Tingkatkan standar...
ReplyDelete:D