Merapikan Rumah Besar
Sebuah inspirasi kecil muncul saat sedang bersih-bersih dan beres-beres rumah. Maklum, tak ada orang yang senang dengan ketidakbersihan ketidakrapian. Siapapun orangnya. Hanya kadarnya yang barangkali berbeda-beda. Ketika tengah berkerja, saya pun teringat dengan ajaran orangtua saya waktu masih kecil. Intinya, beliau mengatakan kalau untuk rapi sebenarnya gampang: Pastikan sesuatu itu diletakkan pada tempatnya. Hanya itu. Jadi ketika kecil saya sering ditegur orangtua kalau sehabis mandi handuk tidak di’jereng’ kembali di jemuran handuk, atau kalau sehabis pulang sekolah sepatu tidak dimasukkan ke dalam rumah, atau kalau habis main Play Stasion joystik dibiarkan tergeletak begitu saja. Kalau sesekali beliau menyuruh membersihkan rumah, biasanya itu memang karena kondisi alamiah seperti debu yang menempel, daun dari pohon gugur di halaman, dan sejenisnya. Alhamdulillah bukan untuk membersihkan ‘dosa’ saya karena tidak rapi.
Setelah kuliah dan jauh dari orang tua, tak lagi teguran-teguran itu didengar. Maka tak jarang jemuran yang sudah kering tergeletak begitu saja, gelas dan piring yang baru dipakai juga tak lekas dicuci, charger hp tidak langsung disimpan, pun buku-buku yang sudah dibaca tak langsung dirapikan. Alasannya remeh, “nanti saja, kan gampang. Tinggal dibeginikan atau dibegitukan. Beres”. Begitu kira-kira. Sampai akhirnya kamar kelihatan berantakan baru akhirnya dirapikan dan dibersikan. Itu pun setelah mengalokasikan waktu khusus (maklum, saya dulu aktivis yang pergi pagi pulang larut malam, hehehe).
Saya kemudian jadi berpikir, ini mirip dengan analogi sebuah bangsa yang katanya “kacau” atau berantakan. Saya cenderung menyinonimkan istilah berantakan dengan kekacauan. Menurut saya, kekacauan selalu muncul ketika sesuatu hal tidak ditempatkan pada posisinya. Mirip petuah orangtua saya dulu. Pada awalnya, kekacauan itu tarafnya kecil. Hal-hal yang tidak ditempatkan pada tempat semestinya itu masih sedikit dan tergolong perkara sederhana. Sebagian orang terbiasa membuang sampah sembarangan. “Ah, ntar kan ada petugas yang membersihkan”, itu alasannya. Ada juga orang yang tidak menyiram bekas kotorannya di WC Umum. “Gue kan uda bayar seribu. Dia dong yang ngebersihin”, itu dalihnya. Atau orang yang tidak mematikan lampu rumah di siang hari. “Bukan urusan lu, gue bisa bayar biaya listriknya kok”, itu argumennya. Bisa juga sopir angkot yang berhenti di tengah (bener-bener di tengah) jalan, publik figur yang tampil seronok, budaya copas dan ngejiplak tanpa menyebutkan sumber, atau ngedapus awang-awang (nyebut dapus tapi pustakanya bahkan tak disentuh), dan lain-lain yang dibiasakan dan akhirnya mendapat pemakluman. Itu mungkin sederhana tapi karena itu lantas diremehkan. Hasilnya kekacauan demi kekacauan terakumulasi. Semakin banyak hal yang tidak berada pada posisi dan porsinya. Endingnya, bagi insan yang sadar bahwa budaya kita tengah kacau, kita pun bingung mau memulai membereskan kekacauan ini dari mana. Di dunia ‘langit’ sana, elit politik mengelit, PSSI kisruh, parpol-parpol diliputi konflik internal, skandal mafia di mana-mana, perfilman nasional puasa kualitas, industri hiburan makin mengeksploitasi wanita (dan wanitanya malah bangga) dan sebagainya. Belum lagi di dunia ‘bumi’ masih banyak kaum urban yang tak berkompetensi, preman pasar dan terminal pasang lapak di mana-mana, anak putus sekolah bertambah, banjir, hutan makin gundul, satwa-satwa makin langka, ulama sering dihujat, pengangguran makin meningkat, dan lain-lain (pembaca mau nambahin? Hehehe).
Hemat saya itu adalah bentuk kekacauan, karena sesuatu tidak ditempatkan pada posisi dan porsinya. Itu lahir ketika kita memberikan pemakluman terhadap kekacauan-kekacauan kecil. Pemakluman itu kemudian jadi lingkungan yang kondusif untuk kekacauan yang lebih besar, yang akhirnya sebagian mungkin kita maklumi juga. Jadi lalu bagaimana?
Karena awalnya adalah analogi dari beres-beres rumah, maka tak berlebihan kiranya kalau penanggulangannya juga dengan analogi yang sama. Pertama, untuk mencegah bertambahnya kuantitas dan kompleksitas kekacauan, setidaknya kita tidak memberikan pemakluman terhadap kekacauan kecil di sekitar kita. Sesuatu yang ada dalam jangkauan kita, diletakkanlah di posisi yang semestinya. Langsung, seketika itu juga. Meski sederhana. Kedua, ibarat membereskan rumah yang besar, memang tidak bisa SKS (sistem kerja sangkuriang) alias instan. Satu per satu sampah dibereskan, disapu, dibuang, ke tempat sampah. Perkakas yang rusak diganti. Yang berserak dirapikan. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya rumah besar itu jadi bersih dan rapi.
Gampang kan? Ya, jika diucapkan tanpa dikerjakan. Seperti beres-beres rumah. Gampang sekali mengkonsep beres-beresnya. Tapi ketika diaplikasikan, capek juga. Untunglah sudah ada isteri di rumah. Makin banyak yang bekerja, sama visinya, apalagi rekan kerja kita adalah sosok yang dicintai (karena Alloh. red) pekerjaan melelahkan itu pun lebih mudah, ringan, dan menyenangkan. Begitu juga membereskan rumah besar bernama Indonesia ini. Mudah sekali di teorinya. Kenyataannya tentu cukup rumit. Nyaris tak mungkin kita kerjakan sendiri. Perlu banyak orang yang terlibat, lalu sinergi dalam hal teknis, kerja sama, kesamaan visi dan tujuan, serta rasa saling cinta. Kita petakan segala kekacauan, hal-hal yang tidak seharusnya ada di situ dan hal-hal yang seharusnya ada di situ. Lalu kita eksekusi perbaikannya. Tentu semampu kita. Mulai dari yang mampu kita jangkau.
Kawan, jangan pernah pesimis dengan kekacauan ini. Ini peluang amal bagi kita. Jangan juga beranggapan bahwa mengubah bangsa ini jadi lebih baik bukan tugas kita, bukan tanggung jawab kita. Jangan pula merasa bersih dan rapinya negeri ini sebagai utopia belaka. Yakinlah bahwa itu riil adanya. Bisa, selama orang-orang peduli seperti kita masih ada dan masih bersedia bekerja. Dan jangan pernah merasa sia-sia atas kerja kita untuk bangsa, karena sesungguhnya Alloh maha melihat kerja-kerja kita, dan Alloh tak pernah akan menyia-nyiakannya. Wattaqulloh, wa’lamuu annakum mulaaquuh.
Wallohua’lam
Setelah kuliah dan jauh dari orang tua, tak lagi teguran-teguran itu didengar. Maka tak jarang jemuran yang sudah kering tergeletak begitu saja, gelas dan piring yang baru dipakai juga tak lekas dicuci, charger hp tidak langsung disimpan, pun buku-buku yang sudah dibaca tak langsung dirapikan. Alasannya remeh, “nanti saja, kan gampang. Tinggal dibeginikan atau dibegitukan. Beres”. Begitu kira-kira. Sampai akhirnya kamar kelihatan berantakan baru akhirnya dirapikan dan dibersikan. Itu pun setelah mengalokasikan waktu khusus (maklum, saya dulu aktivis yang pergi pagi pulang larut malam, hehehe).
Saya kemudian jadi berpikir, ini mirip dengan analogi sebuah bangsa yang katanya “kacau” atau berantakan. Saya cenderung menyinonimkan istilah berantakan dengan kekacauan. Menurut saya, kekacauan selalu muncul ketika sesuatu hal tidak ditempatkan pada posisinya. Mirip petuah orangtua saya dulu. Pada awalnya, kekacauan itu tarafnya kecil. Hal-hal yang tidak ditempatkan pada tempat semestinya itu masih sedikit dan tergolong perkara sederhana. Sebagian orang terbiasa membuang sampah sembarangan. “Ah, ntar kan ada petugas yang membersihkan”, itu alasannya. Ada juga orang yang tidak menyiram bekas kotorannya di WC Umum. “Gue kan uda bayar seribu. Dia dong yang ngebersihin”, itu dalihnya. Atau orang yang tidak mematikan lampu rumah di siang hari. “Bukan urusan lu, gue bisa bayar biaya listriknya kok”, itu argumennya. Bisa juga sopir angkot yang berhenti di tengah (bener-bener di tengah) jalan, publik figur yang tampil seronok, budaya copas dan ngejiplak tanpa menyebutkan sumber, atau ngedapus awang-awang (nyebut dapus tapi pustakanya bahkan tak disentuh), dan lain-lain yang dibiasakan dan akhirnya mendapat pemakluman. Itu mungkin sederhana tapi karena itu lantas diremehkan. Hasilnya kekacauan demi kekacauan terakumulasi. Semakin banyak hal yang tidak berada pada posisi dan porsinya. Endingnya, bagi insan yang sadar bahwa budaya kita tengah kacau, kita pun bingung mau memulai membereskan kekacauan ini dari mana. Di dunia ‘langit’ sana, elit politik mengelit, PSSI kisruh, parpol-parpol diliputi konflik internal, skandal mafia di mana-mana, perfilman nasional puasa kualitas, industri hiburan makin mengeksploitasi wanita (dan wanitanya malah bangga) dan sebagainya. Belum lagi di dunia ‘bumi’ masih banyak kaum urban yang tak berkompetensi, preman pasar dan terminal pasang lapak di mana-mana, anak putus sekolah bertambah, banjir, hutan makin gundul, satwa-satwa makin langka, ulama sering dihujat, pengangguran makin meningkat, dan lain-lain (pembaca mau nambahin? Hehehe).
Hemat saya itu adalah bentuk kekacauan, karena sesuatu tidak ditempatkan pada posisi dan porsinya. Itu lahir ketika kita memberikan pemakluman terhadap kekacauan-kekacauan kecil. Pemakluman itu kemudian jadi lingkungan yang kondusif untuk kekacauan yang lebih besar, yang akhirnya sebagian mungkin kita maklumi juga. Jadi lalu bagaimana?
Karena awalnya adalah analogi dari beres-beres rumah, maka tak berlebihan kiranya kalau penanggulangannya juga dengan analogi yang sama. Pertama, untuk mencegah bertambahnya kuantitas dan kompleksitas kekacauan, setidaknya kita tidak memberikan pemakluman terhadap kekacauan kecil di sekitar kita. Sesuatu yang ada dalam jangkauan kita, diletakkanlah di posisi yang semestinya. Langsung, seketika itu juga. Meski sederhana. Kedua, ibarat membereskan rumah yang besar, memang tidak bisa SKS (sistem kerja sangkuriang) alias instan. Satu per satu sampah dibereskan, disapu, dibuang, ke tempat sampah. Perkakas yang rusak diganti. Yang berserak dirapikan. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya rumah besar itu jadi bersih dan rapi.
Gampang kan? Ya, jika diucapkan tanpa dikerjakan. Seperti beres-beres rumah. Gampang sekali mengkonsep beres-beresnya. Tapi ketika diaplikasikan, capek juga. Untunglah sudah ada isteri di rumah. Makin banyak yang bekerja, sama visinya, apalagi rekan kerja kita adalah sosok yang dicintai (karena Alloh. red) pekerjaan melelahkan itu pun lebih mudah, ringan, dan menyenangkan. Begitu juga membereskan rumah besar bernama Indonesia ini. Mudah sekali di teorinya. Kenyataannya tentu cukup rumit. Nyaris tak mungkin kita kerjakan sendiri. Perlu banyak orang yang terlibat, lalu sinergi dalam hal teknis, kerja sama, kesamaan visi dan tujuan, serta rasa saling cinta. Kita petakan segala kekacauan, hal-hal yang tidak seharusnya ada di situ dan hal-hal yang seharusnya ada di situ. Lalu kita eksekusi perbaikannya. Tentu semampu kita. Mulai dari yang mampu kita jangkau.
Kawan, jangan pernah pesimis dengan kekacauan ini. Ini peluang amal bagi kita. Jangan juga beranggapan bahwa mengubah bangsa ini jadi lebih baik bukan tugas kita, bukan tanggung jawab kita. Jangan pula merasa bersih dan rapinya negeri ini sebagai utopia belaka. Yakinlah bahwa itu riil adanya. Bisa, selama orang-orang peduli seperti kita masih ada dan masih bersedia bekerja. Dan jangan pernah merasa sia-sia atas kerja kita untuk bangsa, karena sesungguhnya Alloh maha melihat kerja-kerja kita, dan Alloh tak pernah akan menyia-nyiakannya. Wattaqulloh, wa’lamuu annakum mulaaquuh.
Wallohua’lam
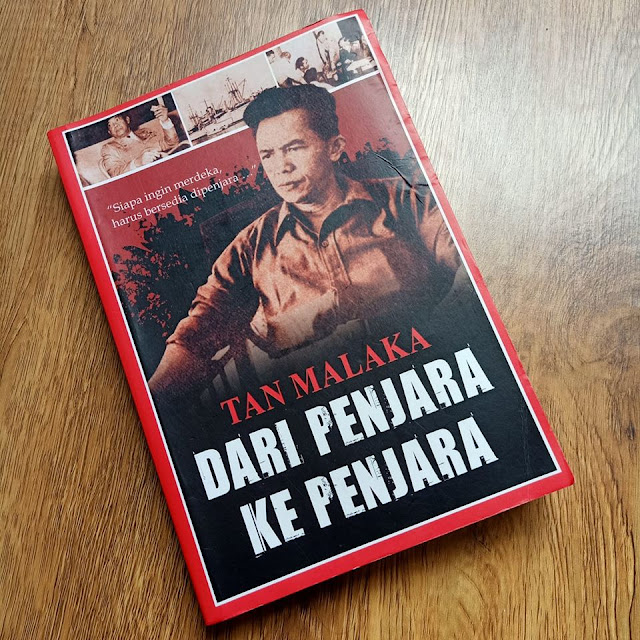
Comments
Post a Comment