UN Kembali ke Tujuan
Seyogianya pendidikan tidak dimaknai sekedar kemampuan siswa menyelesaikan soal-soal kognitif akademis di atas kertas belaka. Tapi lebih jauh dari itu, membentuk kepribadian yang matang baik secara intelektual, emosional, dan spiritual yang tergambar dari sikap hidup sehari-hari.
Pembahasan mengenai pendidikan Indonesia erat kaitannya dengan pembahasan sistem evaluasi yang telah dipakai bertahun-tahun dan tak lepas dari kontroversi, UN atau Ujian Nasional. Sebabnya metode evaluasi untuk melihat hasil proses pembelajaran siswa selama 3 tahun merepresentasikan orientasi yang berakar dalam pola pendidikan itu sendiri. Berkaca dari mekanisme UN yang sudah-sudah, soal UN meliputi empat bidang ilmu yakni Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Bentuk soalnya adalah pilihan berganda yang terdiri dari 50 soal. Siswa yang dinyatakan layak lulus adalah siswa yang mampu menjawab dengan benar setidaknya 55% dari soal yang diberikan. Kurang dari itu, satu kata untuk siswa: Tidak lulus.
Kontroversi mengenai mekanisme ini selalu dibicarakan dari waktu ke waktu. Pihak yang mendukung mekanisme UN yang sekarang beralasan bahwa mutu pendidikan Indonesia dapat ditingkatkan dengan penentuan standar kelulusan yang juga tinggi. Pihak yang menolak beralasan bahwa mekanisme UN tersebut tidak relevan untuk dijadikan standar kelulusan. Tidak tahu bagaimana ujung pembicaraan, namun yang jelas hingga kini UN masih berlangsung dengan modelnya yang konvensional.
Dalam hal ini penulis mencoba menyampaikan kembali gagasan mengenai sistem pendidikan Indonesia berikut metode evaluasi yang dinilai cukup sesuai. Namun sebelum beranjak lebih jauh, diperlukan suatu kata sepakat mengenai orientasi pendidikan itu diadakan dan apa tujuannya sekolah itu dibangun. Dalam pembukaan UUD 45, tercantum salah satu tujuan yang ingin dicapai negeri ini dalam pembangunan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita jujur menilik apa makna cerdas bagi kita, sangat mungkin ada definisi yang berbeda-beda. Namun yang jelas setidaknya ada irisan yang saling bekesesuaian antara satu definisi dengan definisi yang lainnya. Irisan tersebut terletak pada kualitas seseorang yang semakin meningkat. Seorang manusia yang dinilai cerdas (dalam hal apa pun itu) secara otomatis juga akan diniali berkualitas. Semakin cerdas seseorang maka semakin berkualitas dirinya, dan berlaku pula sebaliknya. Masalahnya, aspek kecerdasan dan kualitas termasuk hal yang multidimensi.
Salah satu contoh konkret dapat kita lihat pada apa yang terjadi pada Hee Ah Lee. Dalam aspek intelektual, sosok tersebut memiliki nilai IQ yang jauh di bawah rata-rata. Meskipun demikian, kemampuannya dalam musik tidak berbanding lurus dengan itu. Kemampuannya dalam bermain piano, meski hanya dengan 4 jari, mengundang decak kagum orang-orang yang mendengarnya. Di sini terlihat adanya distingsi antara satu aspek kecerdasan/kualitas dengan aspek kecerdasan/kualitas lainnya. Itu contoh ekstrimnya. Contoh yang lebih moderat dapat kita lihat luas pada anak-anak dan remaja di sekitar kehidupan kita. Kelemahan pada satu hal sangat mungkin disertai keunggulan dalam hal yang lain.
Ilustrasi tersebut mungkin cukup memberikan pengertian pada kita bahwa betapa tidak adilnya ketika kualitas lulusan hanya dinilai dalam 4 aspek mata pelajaran saja. Padahal di sekolah ada mata pelajaran lain yang diajarkan. Pembedaan 4 mata pelajaran yang distandardisasi secara nasional sedangkan yang lain tidak juga menunjukkan sisi diskriminasi dalam pendidikan. Empat mata pelajaran tersebut secara tidak langsung dianggap memiliki bobot lebih dalam kehidupan ketimbang mata pelajaran lainnya.
Bila ditelisik lebih dalam lagi, model soal pilihan berganda juga tidak mampu mengeksplorasi pengetahuan siswa secara komprehensif. Jawaban hanya berkisar pada istilah benar atau salah tanpa ada pembobotan. Dalam soal matematika misalnya, sebuah jawaban merupakan hasil dari serangkaian proses pemahaman dan pemikiran. Ketika sudah dikerahkan daya upaya dan pada akhirnya terdapat satu kekeliruan yang menyebabkan salahnya jawaban, makan daya upaya dan pemikiran yang dimiliki tersebut diberi nilai nol. Tidak ada nilai atas proses berpikir. Di sisi lain, mereka yang beruntung menebak dengan benar jawaban tanpa melalui proses berpikir akan diberi nilai 1. Dalam pelaksanaannya akan sangat banyak variasi yang terjadi. Namun yang jelas, ilustrasi tersebut memperlihatkan gambaran yang tidak seimbang dalam sebuah penilaian proses pembelajaran.
Tulisan ini bukanlah sebuah pernyataan bahwa UN tidak dibutuhkan. Secara jelas, UN memiliki arti penting dalam pendidikan Indonesia. khususnya dalam hal pemetaan kemampuan siswa. Namun demikian, arti penting tersebut akan tereduksi dan salah kaprah ketikda dijadikan standar kelulusan siswa. Karena UN tidak mampu melihat kontinuitas dan kompleksitas serta kualitas proses pembelajaran yang sudah dialami siswa selama 3 tahun. Pertanyaan sederhananya, apakah siswa yang tidak lulus UN berarti siswa tersebut buruk dalam aktivitas belajarnya selama di sekolah?Mungkin iya tapi juga sangat mungkin tidak. Kecuali, akan berbeda ceritanya jika semua orang sepakat bahwa, "Pendidikan adalah seperangkat mekanisme untuk membuat siswa mampu mengerjakan soal-soal pilihan berganda IPA, Matematika, BI, dan B Ing.". JIka itu yang terjadi, maka masalah pun selesai, dan kontroversi pun akan hilang dengan sedirinya.
Pembahasan mengenai pendidikan Indonesia erat kaitannya dengan pembahasan sistem evaluasi yang telah dipakai bertahun-tahun dan tak lepas dari kontroversi, UN atau Ujian Nasional. Sebabnya metode evaluasi untuk melihat hasil proses pembelajaran siswa selama 3 tahun merepresentasikan orientasi yang berakar dalam pola pendidikan itu sendiri. Berkaca dari mekanisme UN yang sudah-sudah, soal UN meliputi empat bidang ilmu yakni Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Bentuk soalnya adalah pilihan berganda yang terdiri dari 50 soal. Siswa yang dinyatakan layak lulus adalah siswa yang mampu menjawab dengan benar setidaknya 55% dari soal yang diberikan. Kurang dari itu, satu kata untuk siswa: Tidak lulus.
Kontroversi mengenai mekanisme ini selalu dibicarakan dari waktu ke waktu. Pihak yang mendukung mekanisme UN yang sekarang beralasan bahwa mutu pendidikan Indonesia dapat ditingkatkan dengan penentuan standar kelulusan yang juga tinggi. Pihak yang menolak beralasan bahwa mekanisme UN tersebut tidak relevan untuk dijadikan standar kelulusan. Tidak tahu bagaimana ujung pembicaraan, namun yang jelas hingga kini UN masih berlangsung dengan modelnya yang konvensional.
Dalam hal ini penulis mencoba menyampaikan kembali gagasan mengenai sistem pendidikan Indonesia berikut metode evaluasi yang dinilai cukup sesuai. Namun sebelum beranjak lebih jauh, diperlukan suatu kata sepakat mengenai orientasi pendidikan itu diadakan dan apa tujuannya sekolah itu dibangun. Dalam pembukaan UUD 45, tercantum salah satu tujuan yang ingin dicapai negeri ini dalam pembangunan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika kita jujur menilik apa makna cerdas bagi kita, sangat mungkin ada definisi yang berbeda-beda. Namun yang jelas setidaknya ada irisan yang saling bekesesuaian antara satu definisi dengan definisi yang lainnya. Irisan tersebut terletak pada kualitas seseorang yang semakin meningkat. Seorang manusia yang dinilai cerdas (dalam hal apa pun itu) secara otomatis juga akan diniali berkualitas. Semakin cerdas seseorang maka semakin berkualitas dirinya, dan berlaku pula sebaliknya. Masalahnya, aspek kecerdasan dan kualitas termasuk hal yang multidimensi.
Salah satu contoh konkret dapat kita lihat pada apa yang terjadi pada Hee Ah Lee. Dalam aspek intelektual, sosok tersebut memiliki nilai IQ yang jauh di bawah rata-rata. Meskipun demikian, kemampuannya dalam musik tidak berbanding lurus dengan itu. Kemampuannya dalam bermain piano, meski hanya dengan 4 jari, mengundang decak kagum orang-orang yang mendengarnya. Di sini terlihat adanya distingsi antara satu aspek kecerdasan/kualitas dengan aspek kecerdasan/kualitas lainnya. Itu contoh ekstrimnya. Contoh yang lebih moderat dapat kita lihat luas pada anak-anak dan remaja di sekitar kehidupan kita. Kelemahan pada satu hal sangat mungkin disertai keunggulan dalam hal yang lain.
Ilustrasi tersebut mungkin cukup memberikan pengertian pada kita bahwa betapa tidak adilnya ketika kualitas lulusan hanya dinilai dalam 4 aspek mata pelajaran saja. Padahal di sekolah ada mata pelajaran lain yang diajarkan. Pembedaan 4 mata pelajaran yang distandardisasi secara nasional sedangkan yang lain tidak juga menunjukkan sisi diskriminasi dalam pendidikan. Empat mata pelajaran tersebut secara tidak langsung dianggap memiliki bobot lebih dalam kehidupan ketimbang mata pelajaran lainnya.
Bila ditelisik lebih dalam lagi, model soal pilihan berganda juga tidak mampu mengeksplorasi pengetahuan siswa secara komprehensif. Jawaban hanya berkisar pada istilah benar atau salah tanpa ada pembobotan. Dalam soal matematika misalnya, sebuah jawaban merupakan hasil dari serangkaian proses pemahaman dan pemikiran. Ketika sudah dikerahkan daya upaya dan pada akhirnya terdapat satu kekeliruan yang menyebabkan salahnya jawaban, makan daya upaya dan pemikiran yang dimiliki tersebut diberi nilai nol. Tidak ada nilai atas proses berpikir. Di sisi lain, mereka yang beruntung menebak dengan benar jawaban tanpa melalui proses berpikir akan diberi nilai 1. Dalam pelaksanaannya akan sangat banyak variasi yang terjadi. Namun yang jelas, ilustrasi tersebut memperlihatkan gambaran yang tidak seimbang dalam sebuah penilaian proses pembelajaran.
Tulisan ini bukanlah sebuah pernyataan bahwa UN tidak dibutuhkan. Secara jelas, UN memiliki arti penting dalam pendidikan Indonesia. khususnya dalam hal pemetaan kemampuan siswa. Namun demikian, arti penting tersebut akan tereduksi dan salah kaprah ketikda dijadikan standar kelulusan siswa. Karena UN tidak mampu melihat kontinuitas dan kompleksitas serta kualitas proses pembelajaran yang sudah dialami siswa selama 3 tahun. Pertanyaan sederhananya, apakah siswa yang tidak lulus UN berarti siswa tersebut buruk dalam aktivitas belajarnya selama di sekolah?Mungkin iya tapi juga sangat mungkin tidak. Kecuali, akan berbeda ceritanya jika semua orang sepakat bahwa, "Pendidikan adalah seperangkat mekanisme untuk membuat siswa mampu mengerjakan soal-soal pilihan berganda IPA, Matematika, BI, dan B Ing.". JIka itu yang terjadi, maka masalah pun selesai, dan kontroversi pun akan hilang dengan sedirinya.
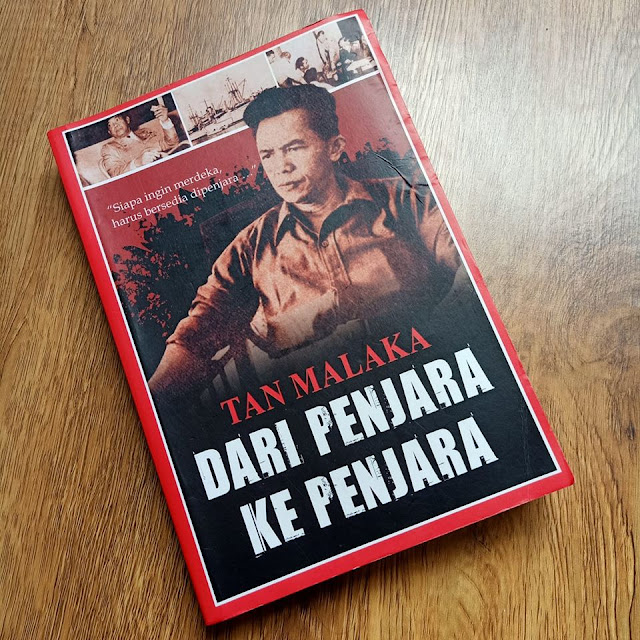
Comments
Post a Comment