Kembali Menjadi Anak Kecil Bersama Na Willa
Bila ada satu kata untuk menggambarkan buku ini, maka kata itu adalah: nostalgia. Pertama adalah karena buku ini bercerita tentang perspektif polos Na Willa, seorang anak usia taman kanak-kanak, dalam memandang dunia dan hal-hal sederhana di sekelilingnya. Perspektif semacam itu saya yakin akan terasa familiar bagi kita karena kita semua pasti pernah punya. Baik disadari atau tidak. Kedua adalah karena latar cerita Na Willa ada di masa lalu, pada era ketika radio dan kaset berpita masih merupakan sarana entertainment yang umum. Belum ada handphone tentu saja. TV masih jadi barang mewah. Bandara di Jakarta bahkan masih ada di Kemayoran. Banyak pernik-pernik dalam cerita ini yang akan membuat kita merasa related dan tentunya jadi turut mengingatkan masa kita kecil.
Buku ini adalah buku kedua yang bercerita soal Na Willa. Sebelumnya, Reda Gaudiamo selaku sang penulis sudah pernah membukukan cerita pertamanya di Tahun 2012. Kebetulan saya belum pernah membaca yang itu. Tapi kalau dari review-review, isinya kurang lebih mirip.
Na Willa adalah seorang anak keturunan Tionghoa yang tinggal di Surabaya. Rumahnya ada di dalam gang. Tiap Minggu orangtuanya rajin mengajaknya ke gereja. Tapi sehari-hari ia akrab dengan teman-teman dan tetangganya yang muslim. Tidak ada yang spesial di alur ceritanya. Hanya deskripsi dari seorang Na Willa. Tentang temannya, tentang teman ayahnya, tentang mainan barunya, tentang tantenya, tentang kebosanannya, tentang hal-hal normal lainnnya. Tapi kekuatan dari cerita Na Willa memang ada pada perspektifnya yang terasa dekat. Dan hangat. Tanpa pretensi, tanpa curiga. Khas anak-anak.
Na Willa adalah bacaan yang ringan, ringkas dan sederhana. Cocok jadi teman minum kopi atau mungkin minum teh di sore hari. Tebalnya bahkan tidak sampai 200 halaman. Namun ada beberapa kesan cukup kuat yang saya dapatkan seusai membacanya. Pertama soal isu multikulturalisme dan toleransi. Hidup menjadi minoritas bisa dijalani tanpa harus ada perasaan canggung. Semuanya bisa bersikap saling menerima dan diterima. Banyak konsep yang sesungguhnya penting namun disimbolisasi dengan hal yang remeh-temeh. Tokoh Mak misalnya, berulang kali menasehati Na Willa bahwa hanya karena Endang terbiasa pakai bedak orang dewasa tidak berarti Na Willa harus melakukannya juga. Orang tua Endang punya alasan untuk membolehkan, dan Mak juga punya alasan untuk melarang. Selain itu Na Willa juga kata Mak tak perlu memaksakan diri menulis dengan tangan kanan seperti teman-temannya, kalau memang dia lebih nyaman menulis dengan tangan kiri (kidal). Pesannya jelas, bahwa sama sekali tak mengapa menjadi berbeda.
Kesan kedua, adalah soal perasaan hangat yang hadir saat membaca ceritanya. Seolah saya tengah minum bandrek ketika dingin-dingin di malam hari. Kadang kehidupan orang dewasa itu memang agak sedikit menyebalkan. Segalanya terasa sudah ter-template, terprogram dengan scenario if-then. Di momen-momen seperti itu, bermuhasabah dengan kembali mencoba berpikir seperti anak kecil rasanya tidak ada salahnya, yang serba ingin tahu, terbuka dengan segala kemungkinan, dan menganggap hal-hal baru sebagai sesuatu yang menyenangkan.
Kesan ketiga adalah tentang menjadi orangtua yang lebih bijak. Saat tulisan ini dibuat, saya punya anak yang seusia Na Willa. Oleh karenanya boleh jadi perspektif Na Willa dalam buku ini adalah cerminan dari perspektif anak saya sendiri. Akibatnya saya pun merasa harus lebih peka. Tanggung jawab saya sebagai ayah adalah memastikan fase di usia itu dapat mereka jalani dengan ceria sehingga bisa jadi kenangan manis saat mereka besar.
Bagi pecinta sastra, novel, dan karya-karya fiksi buku ini sepertinya cukup baik untuk menjadi wishlist bacaan. Btw, saya selalu punya motto “simple is beautiful”, sederhana itu cantik, menarik. Dan buku Na Willa ini menjadi contoh sangat pas, bahwa motto itu benar adanya.
--------
Judul: Na Willa dan Rumah dalam Gang
Penerbit: POST Press (2018)
Penulis: Reda Gaudiamo
Ilustrator: Cecilia Hidayat
Tebal: 170 Hal

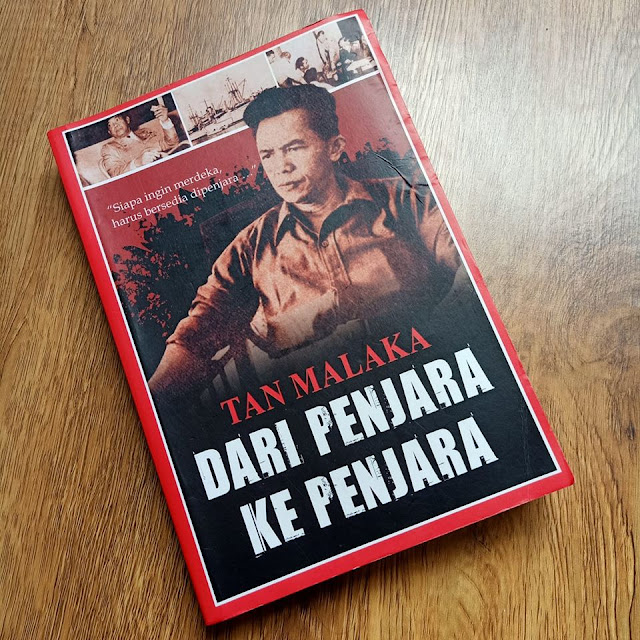
Comments
Post a Comment