Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat [Resensi]
 Bagian terbaik dari buku ini ada di bagian akhirnya. Inti yang saya tangkap dari seluruh pembahasannya adalah tuntunan untuk fokus pada apa yang penting. Masa bodo dengan hal-hal yang gak penting. Penting atau gak penting lantas diperoleh dari refleksi kita atas kematian. Karena ujung-ujungnya kita bakal mati, maka menyibukkan diri dengan urusan remeh temeh itu jadi gak relevan. Menangisi nasib dan gak kunjung move on itu jadi gak relevan. Mencari pelarian dengan obat-obatan dan pergaulan bebas itu jadi gak relevan. Karena ujung-ujungnya kita bakal mati, maka hiduplah dengan bermakna.
Bagian terbaik dari buku ini ada di bagian akhirnya. Inti yang saya tangkap dari seluruh pembahasannya adalah tuntunan untuk fokus pada apa yang penting. Masa bodo dengan hal-hal yang gak penting. Penting atau gak penting lantas diperoleh dari refleksi kita atas kematian. Karena ujung-ujungnya kita bakal mati, maka menyibukkan diri dengan urusan remeh temeh itu jadi gak relevan. Menangisi nasib dan gak kunjung move on itu jadi gak relevan. Mencari pelarian dengan obat-obatan dan pergaulan bebas itu jadi gak relevan. Karena ujung-ujungnya kita bakal mati, maka hiduplah dengan bermakna.
Sejujurnya saya gak nyangka buku ini bisa sampai ke kesimpulan sedalam ini. Soalnya, sejak awal narasi yang penulis kedepankan seolah lepas dari hal-hal yang berbau norma, moral, dan semacamnya. Lihat saja judul aslinya, A Subtle Art of Not Giving a F*ck. Saya yakin, buku edisi terjemahan yang saya baca ini banyak menyensor beberapa istilah asli yang penulis gunakan.
Tapi isi pesannya memang bagus sih. Kita pertama-tama disuruh belajar nrimo, gak banyak protes sama keadaan, mengambil tanggung jawab atas nasib yang kita alami alih-alih menyalahkan orang lain. Lalu kita diajak untuk menyadari kalau kita sebenarnya gak istimewa. Karena kita gak istimewa, maka kita gak berhak menuntut diistimewakan. Perasaan ini lantas kita gunakan untuk membangun etos proaktif. Mau sukses? Berjuang dong. Mau bangkit dari kegagalan? Berusaha dong. Jangan memble. Jangan cengeng. Hidup ini memang seperti jalan terjal, berbatu dan penuh onak duri. Berharap hidup yang sebaliknya itu gak realistis. Begitu kira-kira.
Lalu agar bisa berkembang, pada bagian berikutnya kita diminta agar membuka diri pada pengalaman-pengalaman baru. Pengetahuan baru. Gak ada pengetahuan yang statis. Hari ini kita salah. Besok lusa pun kita masih akan salah. Tapi kalau kita mau terus belajar, kadar kesalahan kita harusnya semakin sedikit dari hari-ke hari. Begitu terus hingga di akhir kita lebih dekat dengan pemahaman yang benar.
Sebenarnya pesan-pesan ini bukan sesuatu yang unik sih. Kalau kita terbiasa membaca buku-buku pengembangan diri, kita akan sering ketemu pesan-pesan serupa. Namun, tiap buku kadang punya pendekatan yang berbeda-beda dalam menjelaskan suatu konsep. Jadi meskipun inti pesannya sama, sudut pandang kita melihatnya bisa beda. Itu tentu saja memperkaya pemahaman kita.
Hal yang saya nilai kurang dari buku ini adalah alur pikir penulis yang kadang terasa random. Acak. Tiba-tiba muncul bahasan ini, setelah sebelumnya membahas hal yang sama sekali berbeda. Bahkan untuk beberapa kasus saya merasa ada konsep yang kontradiktif. Di bab awal penulis bilang apa, di bab berikutnya dia bilang hal yang beda lagi. Mungkin gak benar-benar beda, hanya perlu ditempatkan sesuai konteksnya. Oleh karena itu perlu kejelian dalam mengartikulasikan semua pesan-pesannya.
Ini bukan buku yang jelek. Hanya tidak terlalu istimewa saja. Manfaat terbesar yang saya petik adalah dia mengingatkan kembali saya kebiasaan pertama di buku 7 Habits-nya Stephen R Covey: Proaktif. Selain itu pada titik tertentu, bahasannya memberikan inspirasi untuk bermuhasabah terkait sikap qona’ah yang diajarkan agama. Merasa cukup atas apa yang ada, tapi pada saat yang bersamaan terus mengisi hidup dengan karya-karya yang bermakna.
Karena ujung-ujungnya kita akan mati.
Dan seperti kata Heiji di komik Detektif Conan, kematian adalah alasan kenapa hidup kita ini ada nilainya.
Wallohua’lam.
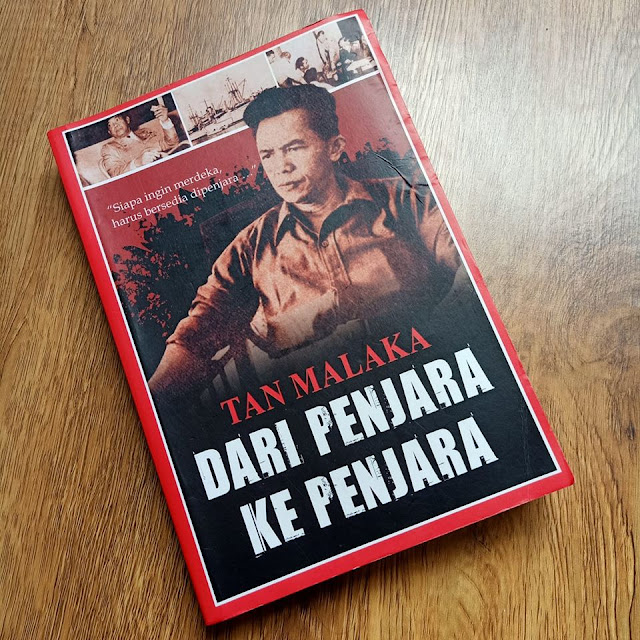
Comments
Post a Comment