Anak Cucu para Samurai
Jepang memang dikenal sebagai bangsa yang tangguh. Bukan hanya karena mereka berhasil menunjukkan kebangkitan setelah hancur-hancuran saat kalah di Perang Dunia II. Bukan juga hanya karena mereka mampu menjadi raksasa perekonomian dan teknologi di dunia. Bukan pula karena mereka punya sejarah, seni, dan kultur yang tak henti-henti diceritakan manusia. Samurai, ninja, origami, dan sebagainya. Tapi lebih karena ada spirit yang sepertinya sudah jadi milik semua masyarakatnya. Spirit yang spektrumnya tidak lagi dalam skala individu, tapi sudah kolektif. Spirit bushido.
Gempa, tsunami, dan ancaman ledakan PLTN Fukushima di pertengahan Maret tahun ini jadi saksinya. Banyak sekali pihak yang memandang Jepang (baik pemerintah, perangkatnya, maupun masyarakatnya) telah sangat efektif menangani musibah yang tak terduga-duga itu. Relokasi pengungsi dan penempatan mereka, alokasi bantuan, antisipasi kemungkinan bahaya lanjutan, hingga kampanye informasi yang memberdayakan dilakukan secara efektif dan seolah terencana dengan baik. Media setempat pun mendukungnya dengan menyampaikan berita, tayangan, ataupun cuplikan yang alih-alih membuat bersedih, tapi sebaliknya malah menyemangati untuk terus saling bekerja sama. Bahu membahu mengatasi persoalan. Lebih detailnya, pembaca bisa menyimak sendiri di berita-berita maupun jejaring sosial.
Ada juga kabar tentang aksi spektakuler sosok-sosok istimewa, para pekerja PLTN yang konon rela mengorbankan nyawa. Kebocoran akibat gempa dan tsunami di sebuah reaktor nuklir mengakibatkan meluasnya radiasi radioaktif yang mengancam keselamatan jiwa banyak warga, hingga radius puluhan km. Tentu tak ada yang mau sukarela tinggal di sana dan terkena radiasi. Tapi itu tidak berlaku untuk pekerja-pekerja istimewa itu. Dengan peralatan seadanya (dibandingkan dengan ancaman radiasi) mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan mengawasi sekaligus menangani reaktor bermasalah itu. Pasalnya, bila reaktor dibiarkan begitu saja, kerusakannya akan semakin parah, komponen reaktor bisa meleleh, dan menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar ketimbang sekedar kebocoran. Ledakan reaktor. Mirip seperti di Chernobyl beberapa dekade lalu. Para pekerja yang tinggal itu bersedia dengan sukarela menjadikan keselamatan mereka sebagai taruhan untuk menjaga keselamatan orang banyak. Terpapar radiasi dan mati. Secara singkat, aktivitas mereka lebih mirip misi bunuh diri, kamikaze.
Tentu kisah di atas bukan hanya kisah satu-dua orang saja. Itu kisah sekumpulan orang. Tapi justru di situlah letak keistimewaannya. Ada semangat kolektif di sana untuk berkorban. Ada pengorbanan kolektif untuk menjaga sesuatu yang mereka anggap lebih berharga ketimbang hidup mereka sendiri. Saya jadi teringat film “Letters from Iwo Jima” yang konon diangkat dari kisah nyata. Para serdadu Jepang, pada saat itu, rela bertahan di pulau terluar Jepang, tanpa bantuan dari unit utama pasukan kekaisaran saat digempur tentara sekutu. Di tengah kondisi yang serba minim, makanan, obat-batan, air, dan amunisi, mereka tahu mereka akan kalah dan Iwo Jima akan diduduki. Tapi mereka memilih untuk mati dalam perjuangan menahan gerak langkah serdadu sekutu. Satu menit pun berharga, pikir mereka. Endingnya, tak ada lagi yang tersisa di pulau itu selain puing-puing senjata dan tumpukan surat-surat mereka. Dari 20.000an orang Jepang yang ada, tidak lebih dari 2000an saja yang “selamat”.
Maka tak heran jika kemudian spirit-spirit itu bertahan di anak cucu mereka seperti sekarang ini. Jika selama ini saya hanya bisa melihat kebesaran bangsa Jepang lewat manga-manga, anime, atau film-film mereka seperti “The Last Samurai”, “Samurai X”, “Musashi”, dan sejenisnya, maka momen kali ini saya seolah disuguhkan di kehidupan nyata. Dalam hati, saya berpikir, mereka memang layak menjadi pewaris para samurai yang legendaris itu.
Jepang memang bukan bangsa yang sempurna. Sebagaimana bangsa-bangsa lainnya di dunia, seperti juga bangsa Indonesia, ada sederet kekurangan yang akan kita temukan kalau dicari-cari. Tapi tentu bukan sikap yang efektif kalau kita gemar mencari-cari dan mengingat-ingat kekurangan. Jauh lebih memberdayakan kalau sesuatu yang baik itu kita tiru. Lalu kita jadikan sifat baik itu melekat pada bangsa kita agar bisa jadi sama-sama baik atau bahkan lebih baik. Di sini, kita setidaknya perlu belajar dari efektivitas penanganan bencana yang didemonstrasikan Jepang, serta spirit pengorbanan mereka untuk melindungi kepentingan umum. Setelah itu kita implementasikan. Saya kira, itu sikap yang jauh lebih berharga ketimbang kasak-kusuk mencerca bangsa sendiri.
Wallohua’lam
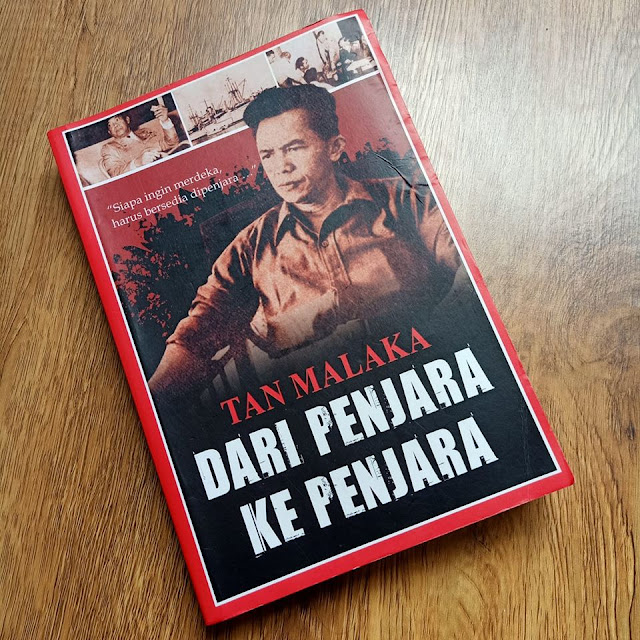
Comments
Post a Comment