Atas Nama Dakwah
Tidak terasa perjalanan studi S1 di tanah seberang sudah mencapai zona ujung. Sedikit lagi dan gelar sarjana akan melekat di belakang nama. Bersama dengan perjalanan itu, tak sedikit pengalaman berharga telah dilewati. Dan satu dimensi pengalaman yang tak terlupakan adalah pengalaman bersama kegiatan dakwah kampus.
Keterlibatan dalam aktivitas dakwah itu bermula dari semangat muda sekaligus keinginan untuk memenuhi amanat masyarakat kampung, menjaga diri dari fitnah dunia. Dengan diawali kondisi yang awam dan sederhana, dimulailah sebuah perjalanan yang tidak bisa dibilang sederhana. Kegiatan pengajian serta aktivtas lainnya yang diselenggarakan oleh aktivis masjid cukup menarik untuk diikuti. Dan tidak ada salahnya memang untuk diikuti.
Hingga kemudian, sosok sederhana itu sudah cukup berilmu dan sedikit lebih mengerti mengenai dunia pergerakan dakwah. Dakwah yang pada hakekatnya tidak layak hanya dimaknai sebagai ceramah satu arah, mulai menunjukkan eksistensinya. Khususnya di kampus. Beragam aktivitas yang kasat mata sebagai aktivitas mahasiswa biasa, diklaim sebagai bagian dari dakwah. Mengingat substansi kegiatan tersebut yang memang sangat berpeluang untuk mendapat sibghah Alloh. Dan hal-hal seperti itulah yang terus terjadi, dialami, bahkan dilakukan.
Berkaca dan berbicara mengenai dakwah, terlebih mengarah pada sebuah konsep gerakan, tidak lepas dari kontroversi. Terlebih yang ada di Kampus seperti IPB, ITB, UI, atau UGM. Berbedanya tingkat pemahaman serta yang memberikan pemahaman tersebut merupakan pemicu utamanya. Perjalanan yang dilakukan juga tak lepas dari itu. Lebih tepatnya, selalu menuai kontroversi di internal. Ada berbagai macam hal yang bisa dicermati dan layak untuk dijadikan sebuah kontroversi. Tapi tentu saja, kontroversi itu tak disengaja. Kemunculannya didasari oleh keinginan untuk mencari solusi atau minimal mengetahui apa yang belum diketahui.
Hal yang mungkin paling hangat adalah eksistensi halaqoh yang menjadi ikon penting kegiatan dakwah utama di kampus-kampus negeri yang cukup besar. Hampir bisa dipastikan, setiap aktivis dakwah ikut serta dalam halaqoh. Dampak sebaliknya, mereka yang tidak ikut serta dalam halaqoh tidak "berhak" diklaim sebagai aktivis dakwah. Apa sebabnya? Ada yang berpendapat bahwa halaqoh adalah bentuk pembinaan utama, sehingga muncul konsep "no halaqoh, no tarbiyah". Kedengarannya cukup ekstrim tapi bagi sebagian orang hal itu lumrah. Pendapat lain mengatakan, halaqoh adalah bentuk pengkaderan lembaga dakwah yang akan memperjuangkan penegakan dinul Islam di Indonesia. Pertanyaannya: lembaga dakwah seperti apa?
Tulisan ini tidak bermaksud menyinggung eksistensi gerakan dakwah, namun demikian berdasarkan hemat penulis ada pendapat-pendapat yang perlu diakomodir. Mencermati pendapat pertama yang menyatakan bahwa no halaqoh no tarbiyah, mungkin memang ada aspek isrof (berlebihan) di sana. Meskipun Rasulullah saw pernah mencontohkannya ketika periode dakwah awal di Makkah, tidak ada ketentuan syar'i khusus yang 'mewajibkan' halaqoh sebagai sarana pembinaan. Di sini, kata 'sarana' menjadi kata kunci. Jika memang sebuah sarana cukup efektif untuk mencapai tujuan, akan sangat baik sarana itu digunakan. Ketika metode halaqoh dinilai cukup efektif untuk mencapai tujuan dakwah, maka silakan saja metode tersebut dilakukan. Masalahnya adalah ketika sarana dijadikan sebagai substansi. Jika itu yang terjadi, salah kaprah yang muncul. Akan lebih parah lagi ketika sarana tersebut dijadikan sandaran dalam melakukan justifikasi terhadap seseorang.
Untuk pendapat kedua, halaqoh yang digunakan sebagai sarana kaderisasi sepertinya cukup realistis. Eksistensi dan keberlanjutan sebuah organisasi akan sangat ditentukan oleh proses kaderisasi. Semakin banyak kader, semakin besar peluang organisasi itu untuk beraktivitas dan meregenerasi diri. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada masalah di sana. Masalah muncul ketika adanya ketidaktransparanan mekanisme penjaringan. Dalam kasus di Kampus, hampir pasti yang diajak dalam halaqoh adalah mahasiswa yang pada gilirannya akan ditawarkan untuk menjadi bagian dari organiasi tersebut, meski tidak secara langsung. Mahasiswa merupakan elemen masyarakat yang paling potensial untuk itu. Kampus sering dicitrakan sebagai lembaga netral yang bebas dari infiltrasi ormas, LSM, apalagi parpol. Jika kaderisasi organisasi-organisasi seperti itu secara struktural berhubungan dengan dan atau melibatkan komponen kampus, dikhawatirkan independensi kampus akan tereduksi. Ceritanya akan berbeda jika penjaringan tersebut menggunakan sarana di luar kampus yang sedari awal secara jelas juga menisbatkan kegiatan pada lembaga yang akan mengakader, tentunya tidak akan ada masalah.
Dakwah menjadi sorotan. Bagi sebagian orang, istilah tersebut mungkin cukup membuat alergi. Untuk itulah para pelakunya (dai) hendaknya menjelaskan secara gamblang pada masyarakat yang ingin tahu. Jika ada kekeliruan pemahaman akibat perbedaan pengertian atau persepsi, sudah selayaknya diluruskan.
[Bersambung]
Keterlibatan dalam aktivitas dakwah itu bermula dari semangat muda sekaligus keinginan untuk memenuhi amanat masyarakat kampung, menjaga diri dari fitnah dunia. Dengan diawali kondisi yang awam dan sederhana, dimulailah sebuah perjalanan yang tidak bisa dibilang sederhana. Kegiatan pengajian serta aktivtas lainnya yang diselenggarakan oleh aktivis masjid cukup menarik untuk diikuti. Dan tidak ada salahnya memang untuk diikuti.
Hingga kemudian, sosok sederhana itu sudah cukup berilmu dan sedikit lebih mengerti mengenai dunia pergerakan dakwah. Dakwah yang pada hakekatnya tidak layak hanya dimaknai sebagai ceramah satu arah, mulai menunjukkan eksistensinya. Khususnya di kampus. Beragam aktivitas yang kasat mata sebagai aktivitas mahasiswa biasa, diklaim sebagai bagian dari dakwah. Mengingat substansi kegiatan tersebut yang memang sangat berpeluang untuk mendapat sibghah Alloh. Dan hal-hal seperti itulah yang terus terjadi, dialami, bahkan dilakukan.
Berkaca dan berbicara mengenai dakwah, terlebih mengarah pada sebuah konsep gerakan, tidak lepas dari kontroversi. Terlebih yang ada di Kampus seperti IPB, ITB, UI, atau UGM. Berbedanya tingkat pemahaman serta yang memberikan pemahaman tersebut merupakan pemicu utamanya. Perjalanan yang dilakukan juga tak lepas dari itu. Lebih tepatnya, selalu menuai kontroversi di internal. Ada berbagai macam hal yang bisa dicermati dan layak untuk dijadikan sebuah kontroversi. Tapi tentu saja, kontroversi itu tak disengaja. Kemunculannya didasari oleh keinginan untuk mencari solusi atau minimal mengetahui apa yang belum diketahui.
Hal yang mungkin paling hangat adalah eksistensi halaqoh yang menjadi ikon penting kegiatan dakwah utama di kampus-kampus negeri yang cukup besar. Hampir bisa dipastikan, setiap aktivis dakwah ikut serta dalam halaqoh. Dampak sebaliknya, mereka yang tidak ikut serta dalam halaqoh tidak "berhak" diklaim sebagai aktivis dakwah. Apa sebabnya? Ada yang berpendapat bahwa halaqoh adalah bentuk pembinaan utama, sehingga muncul konsep "no halaqoh, no tarbiyah". Kedengarannya cukup ekstrim tapi bagi sebagian orang hal itu lumrah. Pendapat lain mengatakan, halaqoh adalah bentuk pengkaderan lembaga dakwah yang akan memperjuangkan penegakan dinul Islam di Indonesia. Pertanyaannya: lembaga dakwah seperti apa?
Tulisan ini tidak bermaksud menyinggung eksistensi gerakan dakwah, namun demikian berdasarkan hemat penulis ada pendapat-pendapat yang perlu diakomodir. Mencermati pendapat pertama yang menyatakan bahwa no halaqoh no tarbiyah, mungkin memang ada aspek isrof (berlebihan) di sana. Meskipun Rasulullah saw pernah mencontohkannya ketika periode dakwah awal di Makkah, tidak ada ketentuan syar'i khusus yang 'mewajibkan' halaqoh sebagai sarana pembinaan. Di sini, kata 'sarana' menjadi kata kunci. Jika memang sebuah sarana cukup efektif untuk mencapai tujuan, akan sangat baik sarana itu digunakan. Ketika metode halaqoh dinilai cukup efektif untuk mencapai tujuan dakwah, maka silakan saja metode tersebut dilakukan. Masalahnya adalah ketika sarana dijadikan sebagai substansi. Jika itu yang terjadi, salah kaprah yang muncul. Akan lebih parah lagi ketika sarana tersebut dijadikan sandaran dalam melakukan justifikasi terhadap seseorang.
Untuk pendapat kedua, halaqoh yang digunakan sebagai sarana kaderisasi sepertinya cukup realistis. Eksistensi dan keberlanjutan sebuah organisasi akan sangat ditentukan oleh proses kaderisasi. Semakin banyak kader, semakin besar peluang organisasi itu untuk beraktivitas dan meregenerasi diri. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada masalah di sana. Masalah muncul ketika adanya ketidaktransparanan mekanisme penjaringan. Dalam kasus di Kampus, hampir pasti yang diajak dalam halaqoh adalah mahasiswa yang pada gilirannya akan ditawarkan untuk menjadi bagian dari organiasi tersebut, meski tidak secara langsung. Mahasiswa merupakan elemen masyarakat yang paling potensial untuk itu. Kampus sering dicitrakan sebagai lembaga netral yang bebas dari infiltrasi ormas, LSM, apalagi parpol. Jika kaderisasi organisasi-organisasi seperti itu secara struktural berhubungan dengan dan atau melibatkan komponen kampus, dikhawatirkan independensi kampus akan tereduksi. Ceritanya akan berbeda jika penjaringan tersebut menggunakan sarana di luar kampus yang sedari awal secara jelas juga menisbatkan kegiatan pada lembaga yang akan mengakader, tentunya tidak akan ada masalah.
Dakwah menjadi sorotan. Bagi sebagian orang, istilah tersebut mungkin cukup membuat alergi. Untuk itulah para pelakunya (dai) hendaknya menjelaskan secara gamblang pada masyarakat yang ingin tahu. Jika ada kekeliruan pemahaman akibat perbedaan pengertian atau persepsi, sudah selayaknya diluruskan.
[Bersambung]
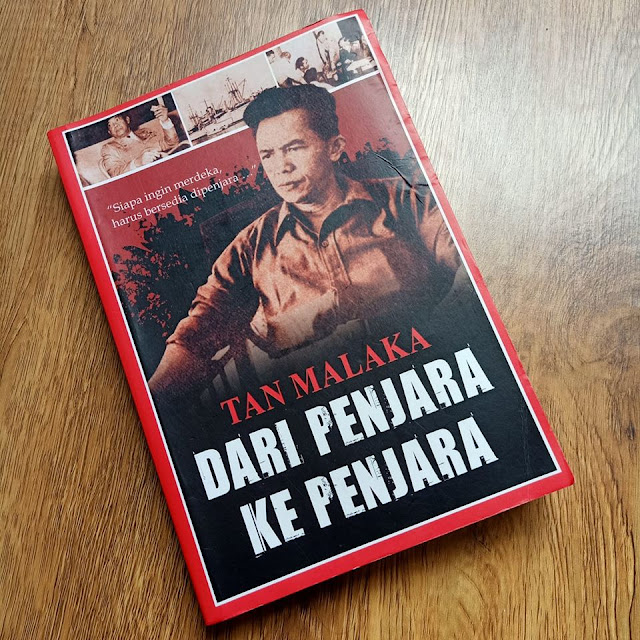
Emm, q tunggu kelanjutannya...
ReplyDelete